- Serangkaian banjir bandang di Pohuwato menelan korban jiwa, menghancurkan rumah warga, dan memicu krisis air bersih yang berlangsung hingga bertahun-tahun. Warga seperti Hasan Lakoro, Ratna Ismail, dan Wani Haniu kehilangan keluarga, rumah, serta sumber penghidupan akibat banjir yang diduga dipicu pembukaan hutan di hulu sungai.
- Dua perusahaan Hutan Tanaman Energi—PT BTL dan PT IGL—dituding menebang ribuan hektare hutan alam untuk memasok bahan baku pelet kayu, sehingga memperparah risiko banjir dan sedimentasi sungai.Data FWI, BNPB, dan kesaksian warga menunjukkan korelasi kuat antara deforestasi di konsesi dua perusahaan itu dengan meningkatnya frekuensi banjir dan kerusakan ekologis sejak 2020.
- Selain banjir, warga di lima kecamatan mengalami krisis air bersih karena sungai menjadi keruh dan tercemar, memaksa mereka membeli air atau mandi di sungai yang menyebabkan gatal-gatal. Meski perusahaan mengklaim aktivitasnya “hijau”, keuntungan ekonomi yang dihasilkan sangat kecil dibanding kerugian sosial-ekologis warga yang ditaksir mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
- Industri pelet kayu Pohuwato terhubung dengan jaringan investasi besar di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan, yang memanfaatkan skema energi terbarukan untuk memasok biomassa ke PLTU lewat ekspor. Paradoksnya, demi memenuhi ambisi energi bersih dua negara maju, hutan tropis Pohuwato ditebang, masyarakat kehilangan kehidupan, dan bencana ekologis terus menghantui wilayah tersebut.
Langit di atas Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Gorontalo, berwarna kelabu pekat sore itu. Bau lumpur dan kayu busuk memenuhi udara. Di tengah lahan becek, Hasan Lakoro berdiri mematung di antara sisa puing rumahnya. Di bawah kakinya, tanah retak dan basah, bekas terjangan air bah yang datang bagai monster yang mengamuk.
Di sana, di tempat yang kini kosong, dulu berdiri rumah sederhana. Dari terasnya, tawa Laras Tiari Lakoro—putri semata wayangnya yang berusia 15 tahun—biasa terdengar hingga ke jalan desa. Kini, yang tersisa hanya foto kecil siswa kelas 3 SMP itu dalam bingkai patah dan suara lirih Hasan, “Dia ditemukan keesokan pagi, di bawah banjir bandang.”
Pada malam Kamis, 20 Juni 2025, hujan deras mengguyur tanpa henti sejak senja. Sekitar pukul sembilan malam, suara gemuruh terdengar dari arah hulu Sungai. Dalam hitungan menit, air cokelat datang menggulung desa, menghancurkan sejumlah rumah, menyeret ternak, dan merenggut dua nyawa: Laras, dan Ance Munu (42), saudara ipar Hasan. Keduanya terjebak di dalam rumah yang akhirnya terseret arus.
Hasan dan istrinya saat itu sedang bekerja di tambang rakyat, sekitar 20 kilometer dari rumah. Kabar banjir datang lewat telepon. Mereka pulang dengan terburu-buru, tapi yang tersisa hanya kehancuran.
“Saya langsung lemas. Istri saya pingsan di tempat,” katanya, menatap ke arah sungai yang kini tinggal aliran kecil berwarna keruh. Laras dan Ance sempat dilaporkan hilang malam itu, dan ditemukan keesokan paginya dalam keadaan tak bernyawa.
Dalam satu malam, Hasan kehilangan segalanya: anak, keluarga, dan rumah. Rumah itu berdiri hanya sepuluh meter dari bantaran sungai. Kini, yang tersisa hanya bekas pondasi. Air naik lebih dari dua meter, menyapu bersih apa pun yang ada di jalurnya. Hasan memperkirakan kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah.
“Tidak ada waktu untuk menyelamatkan apa pun,” katanya pelan. Matanya sembap, suaranya lelah. “Rasanya seperti mimpi buruk.” Dalam hitungan menit, ratusan rumah di Desa Tuweya dan Bohusami terendam. Puluhan rumah rusak berat, ladang serta ternak warga hanyut terbawa arus.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pohuwato, sekitar 1.235 jiwa terdampak banjir bandang di malam itu. Di Desa Tuweya, 158 kepala keluarga atau sekitar 615 jiwa terpaksa mengungsi. Di Desa Bohusami, jumlah pengungsi bahkan lebih besar—197 kepala keluarga atau 620 jiwa.

Pemerintah mengklaim penyebab banjir adalah intensitas hujan tinggi. Tapi bagi Hasan, bencana ini bukan sekadar curah hujan. “Sepanjang hidup saya di desa ini, sungai memang sering meluap. Tapi tidak pernah separah ini. Semua berubah sejak perusahaan itu buka hutan di atas sana,” katanya.
Yang dimaksud Hasan adalah PT Inti Global Laksana (IGL), perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Energi (HTE) di kawasan hulu Wanggarasi.
Kecurigaan Hasan dibenarkan banyak warga. Di Desa Bukit Tinggi, Ratna Ismail juga punya kisah serupa. Kakak kandungnya, Yunus Ismail (53), dan cucu bungsunya, Ramsi Samindi (6), meninggal dunia setelah hanyut di Sungai Popayato pada 18 Juni 2024—setahun sebelum banjir di Tuweya.
Kala itu, Yunus bersama dua cucunya, Ramsi dan Fandli Samindi (13), hendak memindahkan ternak sapi yang digembalakan di seberang sungai. Hujan baru saja reda, dan arus sungai tampak masih tinggi. Tapi mereka tetap nekat menyeberang.
Di tengah sungai, debit air tiba-tiba naik. Arus deras menghantam mereka. Ramsi dan Yunus terseret. Fandli berhasil selamat. Jasad Yunus dan Ramsi ditemukan beberapa hari kemudian, tak jauh dari lokasi kejadian.
“Kami tidak pernah menyangka air sungai bisa secepat itu meluap. Kakak saya sudah puluhan tahun beraktivitas di sungai itu. Tapi kali ini… air datang seperti dinding besar, tidak tertahan,” ucap Ratna, suaranya lirih.
Ratna juga menaruh curiga, dua perusahaan besar sebagai penyebab: PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan IGL—pemegang izin HTE yang menebangi hutan untuk menanam pohon energi seperti gamal dan kaliandra, bahan baku pelet kayu. Ditambah lagi, tambang emas ilegal (PETI) di sekitar hulu memperparah kondisi.
“Hutan sudah gundul. Tanah tidak bisa lagi serap air. Kami yang di bawah jadi korban,” kata Ratna.
Di Desa Lemito Utara, Wani Haniu (48) kehilangan tiga dari empat ekor sapinya. Ternaknya hanyut tersapu banjir bandang. “Sapi saya diikat dekat sungai. Tiba-tiba air datang besar sekali. Tidak sempat apa-apa,” katanya.
Ia memperkirakan kerugian yang dialaminya mencapai puluhan juta rupiah, karena ternak merupakan sumber utama penghidupan keluarga mereka. Di desanya, Wani menceritakan, lebih dari sepuluh ekor sapi warga hanyut terbawa arus dan hingga kini belum ditemukan.
Ia juga menduga dua perusahaan besar di hulu Sungai sebagai penyebab utama: PT BTL dan PT IGL. “Mereka tebang hutan untuk tanam kaliandra dan gamal. Tapi sejak itu, sungai makin sering meluap. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang datang bantu. Pemerintah pun diam saja,” keluhnya.

Air Bersih yang Hilang dari Rumah
Banjir bukan satu-satunya bencana. Setelah hutan di hulu dibuka, sungai-sungai di barat Gorontalo perlahan kehilangan kejernihannya. Air berubah cokelat, dan meninggalkan endapan lumpur di dasar pipa.
Di Desa Bukit Tinggi, Ratna sudah lama berhenti menggunakan air PDAM. “Air dari keran sekarang keruh, kadang berwarna hitam,” katanya. Untuk masak dan minum, ia membeli air galon. Dalam sebulan, keluarganya menghabiskan setengah juta rupiah—jumlah yang besar bagi petani kecil.
Samin Ahmad, warga Desa Bukit Tinggi, juga mengalami hal serupa. Meski begitu, ia dan keluarganya mengaku masih terpaksa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun efek sampingnya mulai terasa.
“Ketika habis mandi sungai, kulit saya dan anak sering jadi merah dan gatal. Walaupun begitu, kita tidak ada pilihan lain,” ujarnya saat ditemui di Sungai Popayato. Ketika itu, ia tengah mandi dan mencuci baju meskipun kondisi air sungai tampak sangat keruh.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, Samin kerap menggali lubang-lubang kecil di pinggiran sungai—semacam sumur resapan yang memanfaatkan filtrasi alami tanah. Airnya sedikit lebih jernih, namun belum tentu aman secara higienis.
Sudah empat tahun mereka hidup dalam kondisi ini. Sejak kawasan hulu dibuka untuk perkebunan energi dan tambang emas ilegal, kondisi sungai berubah drastis. Air yang dulu jernih, kini berubah keruh, penuh endapan lumpur, apalagi saat musim hujan tiba.

Meskipun di hulu juga ada tambang ilegal, Samin juga mencurigai aktivitas BTL dan IGL jadi penyebab utama krisis air bersih yang mereka hadapi. Pembukaan hutan menyebabkan erosi masif dan sedimentasi sungai. Akibatnya, sungai tak lagi mampu menopang kehidupan.
“Ini bukan cuma soal air, ini soal hidup. Kami harus beli air untuk minum dan masak, habiskan lebih dari Rp500 ribu sebulan. Tapi tetap saja harus mandi dan cuci di sungai yang kotor. Kami sangat dirugikan,” tegas Samin.
Situasi yang dialami Samin dan Ratna juga terjadi di Desa Kelapa Lima, Kecamatan Popayato Timur. Yusuf Mese, tokoh masyarakat di sana, mengatakan bahwa krisis air bersih sudah menjadi bagian dari keseharian warga sejak dua perusahaan kebun energi mulai beroperasi di hulu.
“Mereka janji akan bangun bak air bersih untuk warga. Tapi sampai sekarang, jangankan bangunan, papan penandanya saja tidak ada,” kata Yusuf.
Yusuf menyebut janji itu disampaikan dalam sosialisasi awal sebelum perusahaan mulai membuka lahan. Namun, sampai hari ini, tidak satu pun janji direalisasikan. Aduan demi aduan telah disampaikan—mulai dari musyawarah desa, surat resmi, hingga forum publik—namun semua berujung sunyi.
“Kami ini katanya desa dampingan, tapi tidak pernah didampingi, tidak pernah dibantu. Kami dibiarkan hidup di tengah krisis air akibat aktivitas merusak yang mereka lakukan,” ujarnya getir.
Di lima kecamatan—Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, dan Wanggarasi—krisis air kini menjadi kenyataan baru. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan berubah menjadi saluran air kotor penuh endapan. Semua itu diduga terjadi ketika dua perusahaan HTE itu beroperasi.

Tebang Hutan di Wilayah Rawan Bencana
PT BTL dan PT IGL, yang disebut-sebut sebagai pihak utama yang diduga menyebabkan krisis ekologis di Pohuwato, merupakan perusahaan HTE. Keduanya mengklaim menjalankan bisnis yang berkelanjutan dengan menanam tanaman seperti gamal dan kaliandra sebagai bahan baku pelet kayu, yang mereka promosikan sebagai bagian dari sumber energi terbarukan.
Sebelum jadi HTE, kedua perusahaan ini bermula dari perkebunan kelapa sawit. Sejak 2010, BTL dan IGL mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing seluas 16.000 dan 12.000 hektare untuk mengembangkan kebun kelapa sawit. Lokasi konsesi BTL membentang di Kecamatan Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, dan Lemito. Sedangkan wilayah IGL berada di Kecamatan Lemito dan Wanggarasi.
Perubahan arah bisnis terjadi pada Februari 2020, ketika kedua perusahaan mengalihkan izin usaha perkebunan dari kelapa sawit menjadi tanaman energi, yakni gamal dan kaliandra. Kedua komoditas ini belakangan ramai dipromosikan sebagai sumber biomassa hijau untuk produksi pelet kayu.
Tak lama berselang, pada Mei 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyetujui permohonan penetapan hutan hak untuk BTL dan IGL. Luasan hutan hak yang disetujui sebesar 15.493 hektare untuk BTL dan 11.860 hektare untuk IGL. Dengan keputusan ini, total lahan seluas 27.353,53 hektar yang sebelumnya merupakan area perkebunan kelapa sawit, resmi beralih status menjadi HTE.
Adapun bahan baku dari BTL dan IGL disuplai ke PT Biomasa Jaya Abadi (BJA), sebuah perusahaan industri pelet kayu yang juga didirikan di dalam area konsesi. Pelet kayu tersebut nantinya akan dicampurkan dengan batu bara dalam sistem pembakaran yang sama (co-firing) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang diklaim mampu menekan emisi karbon dari sektor energi.
Namun, di balik label “energi hijau”, ekspansi kebun BTL dan IGL justru kerap menimbulkan persoalan baru. Alih-alih memanfaatkan areal non-hutan atau lahan terdegradasi, aktivitas kedua perusahaan HTE itu justru menebang hutan alam yang masih utuh.
Menurut analisis spasial Forest Watch Indonesia (FWI), BTL dan IGL dalam kurun waktu 2021-2024 telah menebang hutan alam seluas 2.793,33 hektar. Adapun menurut analisis spasial Atlas Nusantara, kedua perusahaan itu melakukan deforestasi seluas 3.485,1 hektar dalam periode 2020-2024.
Artinya, sebagian besar kayu yang diproduksi oleh kedua perusahaan HTE ini berasal dari penebangan hutan alam, termasuk kawasan hutan primer—bukan dari hasil penanaman ulang atau rehabilitasi. Praktik ini disinyalir menjadi pemicu meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di Pohuwato, seperti banjir.
“Ini bukan hutan tanaman, ini hutan alam yang ditebang,” kata Anggi Putra Prayoga, Manager Kampanye, Advokasi, Media FWI.
Analisis spasial FWI juga menemukan konsesi dua perusahaan itu tumpang tindih dengan tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pohuwato: Lemito, Popayato, dan Randangan. Selama 2017–2023, deforestasi sepanjang alur ketiga DAS tersebut mencapai 1.274,47 hektar, dengan 15% di konsesi PT BTL (188,51 hektar) dan 2% di konsesi IGL (22,16 hektar).
“Ketika hutan di aliran sungai dibuka, kemampuan tanah menyerap air hilang. Air hujan langsung lari ke bawah. Begitulah banjir bandang lahir,” jelas Anggi.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat dugaan terkait dampak kegiatan pembabatan hutan itu. Sejak dua perusahaan itu beroperasi pada 2020, frekuensi banjir di Kabupaten Pohuwato meningkat secara signifikan, tercatat mencapai 35 kali hingga Oktober 2025.
Dalam periode yang sama, sekitar 13 ribu rumah terendam dan lebih dari 56 ribu jiwa mengungsi. Sebagian besar banjir yang dilaporkan BNPB diduga terjadi di hilir konsesi PT BTL dan PT IGL, sejalan dengan kesaksian warga seperti Hasan Lakoro dan Ratna Ismail, yang kehilangan anggota keluarga akibat bencana ekologis tersebut.
Padahal, kabupaten di ujung barat Gorontalo seharusnya menjadi wilayah yang dijaga kelestariannya, bukan dibuka untuk kegiatan penebangan hutan. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Nasional dari BNPB, kabupaten ini memiliki wilayah dengan tingkat bahaya banjir terbesar di Gorontalo, seluas 41.495 hektare, dengan potensi terdampak sebanyak 87.539 jiwa.
Tak hanya itu, kabupaten ini juga merupakan daerah dengan bahaya cuaca ekstrem terluas, yaitu 137.185 hektare—setara lebih dari sepertiga total kawasan rawan cuaca ekstrem di Provinsi Gorontalo, yang mencapai 384.513 hektare.
“Secara ekologis, wilayah itu sudah lampu merah,” kata Anggi. “Dan ironinya, perusahaan justru memotong hutan di titik paling rawan banjir.”
Anggi menjelaskan, peran hutan dalam mengatur siklus air sangatlah vital, terutama di wilayah dengan kontur berbukit dan aliran sungai yang deras. Ia menduga kuat bahwa penebangan hutan alam serta kerusakan hutan di sekitar tiga DAS menjadi penyebab utama meningkatnya frekuensi dan skala banjir bandang di Pohuwato.
Ia menegaskan bahwa dalam membahas dampak ekologis, aspek legalitas tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kerusakan. Setiap kegiatan berizin, terutama yang menebang hutan alam, wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Jika muncul dampak ekologis, hal itu menandakan perusahaan tidak menjalankan Amdal dengan benar.
Ironisnya, kata Anggi, BTL dan IGL justru diduga bukan hanya tidak menjalankan Amdal-nya, tetapi juga hanya memiliki Amdal untuk perkebunan kelapa sawit, bukan untuk HTE. Menurutnya, menebang hutan dengan menggunakan Amdal sawit merupakan bentuk pelanggaran hukum.
“Kalau mereka menebang hutan alam tapi hanya berbekal Amdal sawit, jelas ada pelanggaran,” ujar Anggi. “Perusahaan-perusahaan ini berisiko tinggi menciptakan dampak ekologis serius bagi masyarakat dari hulu hingga hilir.”
Bukan Untung Malah Buntung
Berbagai bencana ekologis yang melanda Kabupaten Pohuwato belakangan ini menjadi cermin betapa masyarakat menanggung lebih banyak kerugian dibanding manfaat dari proyek yang diklaim “ramah lingkungan”. Kerugian tersebut sebenarnya dapat dihitung secara sederhana.
Meskipun belum ada perhitungan pasti mengenai kerugian ekonomi per rumah akibat banjir, standar bantuan BNPB bisa dijadikan patokan awal. Bantuan perbaikan rumah korban banjir dibagi menjadi tiga kategori: Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat.
Jika standar ini diterapkan pada ribuan rumah warga Pohuwato yang terdampak banjir sepanjang 2020–2025, total bantuan ideal yang semestinya disalurkan pemerintah mencapai sekitar Rp55 miliar. Jumlah itu belum termasuk kerugian ekonomi lain akibat hilangnya sumber penghidupan, kerusakan infrastruktur, dan turunnya kualitas lingkungan.
Namun, angka itu tampak kecil jika dibandingkan dengan temuan Kajian Risiko Bencana BNPB, yang memperkirakan potensi kerugian akibat banjir di Pohuwato bisa mencapai Rp1,251 triliun. Nilai fantastis ini merupakan rekapitulasi dari potensi kerugian fisik dan ekonomi di seluruh wilayah rawan banjir di kabupaten tersebut.
Ironinya, kerugian itu jauh melampaui sumbangan ekonomi dari industri yang selama ini digadang-gadang membawa kesejahteraan. BJA—industri pengolah pelet kayu yang bahan bakunya dipasok oleh BTL dan IGL—hanya menyumbang sekitar Rp200 miliar dalam bentuk devisa ekspor pada 2024.
Perbandingan ini menunjukkan ketimpangan yang nyata: dampak ekologis dan sosial yang harus ditanggung warga jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diklaim perusahaan. Alih-alih menciptakan ekonomi hijau, praktik HTE di Pohuwato justru memunculkan luka ekologis baru.
Panji Kusumo, Peneliti Pemodelan Ekonomi di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menegaskan bahwa logika ekonomi perusahaan yang mengklaim memberikan keuntungan bagi daerah sangat keliru. Menurutnya, perusahaan justru berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Menurut Panji, kehadiran perusahaan—termasuk pembangunan pabrik atau fasilitas industri—sering dipandang sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kenyataannya di lapangan kerap berbeda.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat pernyataan Panji. Sejak perusahaan beroperasi pada 2020, jumlah penduduk miskin di Pohuwato naik dari 28,92 ribu menjadi 29,39 ribu orang pada 2023. Meski turun sedikit pada 2024 menjadi 28,93 ribu, angkanya tetap lebih tinggi dibanding tahun 2020.
“Secara finansial, keuntungan dari operasional perusahaan lebih banyak dinikmati oleh pihak perusahaan, sementara masyarakat lokal hanya memperoleh manfaat terbatas, bahkan sering mengalami kerugian akibat dampak lingkungan,” ujar Panji.
Panji menambahkan bahwa dampak lingkungan dari kehadiran perusahaan tidak hanya merugikan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan kualitas hidup mereka. Sementara itu, perusahaan tetap memprivatisasi keuntungan besar yang diperoleh.
Anggi juga mengungkapkan, banyak nelayan di Pohuwato kini kesulitan mencari ikan karena dilarang melintasi wilayah pemindahan muatan (transhipment) pelet kayu di tengah laut. Aktivitas perusahaan juga menyebabkan sedimentasi yang mencemari pesisir, mengganggu ekosistem laut, dan membuat nelayan harus menangkap ikan lebih jauh dari daratan.
“Kondisi ini meningkatkan biaya operasional nelayan dan menurunkan pendapatan mereka. Semua dampak ini perlu dihitung sebagai kerugian ekonomi,” ujarnya.
Sebenarnya, kata Anggi, sejak awal sudah terlihat indikasi penyimpangan dalam praktik bisnis perusahaan tersebut. Saat mulai beroperasi, BJA melaporkan hanya mengekspor pelet kayu dari dua jenis kayu alam—nyatoh (Palaquium spp., atau nagasari) dan jambu-jambu (Eugenia sp.)—yang keduanya berasal dari hasil tebang habis hutan alam oleh BTL dan IGL.
Setelah kapal MV Lakas berbendera Filipina ditangkap Badan Keamanan Laut RI pada Agustus 2024 karena mengangkut 10.545 metrik ton pelet kayu, BJA tiba-tiba menambah daftar jenis kayu ekspornya. Dari semula hanya dua jenis, kini menjadi enam: jambu-jambu (Eugenia sp.), bayu (Pterospermum celebicum), laban (Vitex pubescens), bintangur (Calophyllum sp.), terap (Artocarpus odoretissimus), dan mendarahan (Myristica sp.).
“Ada indikasi kuat perusahaan melakukan kecurangan pelaporan. Secara ekonomi, negara jelas dirugikan,” kata Anggi.
Ambisi Hijau Jepang dan Korea Selatan
Praktik penebangan hutan alam di Pohuwato sejatinya akibat ambisi “Hijau” Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara industri tersebut tengah berpacu mencapai target transisi menuju energi bersih. Negara Sakura dan Ginseng ini sangat gencar mempromosikan biomassa—khususnya pelet kayu—sebagai sumber energi terbarukan yang dianggap mampu menggantikan peran batu bara di pembangkit listrik mereka.
Korea Selatan menjadi salah satu contoh paling agresif dalam program energi biomassa. Negara ini menggelontorkan miliaran dolar untuk memperluas pemanfaatan biomassa. Sejak 2015, negeri ginseng itu memberikan insentif besar melalui sistem Renewable Energy Certificate (REC) bagi pembangkit listrik yang menggunakan pelet kayu.
Menurut data Solutions for Our Climate (SFOC), industri biomassa di Korea telah menerima sekitar US$ 3,7 miliar subsidi sambil membakar 50 juta ton kayu. Akibat kebijakan itu, konsumsi biomassa tumbuh 42 kali lipat dalam satu dekade, menjadikannya sumber energi terbarukan terbesar di negara tersebut.
Namun, 80 persen bahan baku pelet itu diimpor—separuh dari Vietnam, sisanya dari Rusia, Kanada, Malaysia, dan Indonesia. Menurut data Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, pembangkit listrik berbasis biomassa kini menyumbang 18 persen dari total 53.146 gigawatt listrik dari energi terbarukan Korea.
Jepang tak kalah agresif. Sejak menerapkan mekanisme Feed-in Tariff (FIT) pada 2012, pemerintah Jepang mewajibkan perusahaan listrik membeli energi terbarukan dengan harga tinggi. Sekitar 75 persen dari skema itu diarahkan khusus untuk pembangkit biomassa. Ada sekitar 75 persen dana FIT justru terserap untuk membiayai pembangkit berbasis biomassa.
Bagi Jepang, ini bagian dari kebijakan Green Transformation (GX)—strategi dekarbonisasi nasional. Hasilnya, menurut data Global Environmental Forum (GEF) Jepang, impor pelet kayu melonjak tajam: dari 2.028 ton pada 2020 menjadi 6.831 ton pada 2024. Impor dari Indonesia naik signifikan, dari 3.800 ton pada 2021 menjadi 315.000 ton pada 2024.
Namun, di balik subsidi dan slogan ramah lingkungan dua negara itu, tersimpan paradoks: demi menjaga langit Tokyo dan Seoul tetap biru, hutan tropis di Pohuwato harus ditebang. Hingga ini, BJA tercatat telah mengekspor 376 ribu ton pelet kayu senilai sekitar Rp780 miliar ke Jepang dan Korea Selatan. Semua pelet kayu itu hasil dari deforestasi hutan alam di Pohuwato.

Junichi Mishiba, Direktur Eksekutif Friends of the Earth (FoE) Jepang, mengakui bahwa pelet kayu dari Indonesia memang digunakan untuk pembangkit listrik biomassa di Jepang dan Korea Selatan.
Namun, ia menilai pemerintah kedua negara itu tidak sepenuhnya menyadari, atau bahkan sengaja mengabaikan, fakta bahwa sebagian bahan baku berasal dari praktik yang merusak lingkungan.
Menurut Junichi, perusahaan perdagangan sering mengklaim bahan baku mereka “legal” dan “berkelanjutan,” padahal asalnya dari kawasan yang mengalami deforestasi. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan cenderung mempercayai klaim ini karena dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Indonesia dianggap sudah cukup.
“Meskipun legal, belum tentu lestari,” kata Junichi Mishiba
Misalnya, Undang-Undang Clean Wood Act di Jepang hanya mensyaratkan legalitas asal kayu tanpa menilai keberlanjutan atau dampak sosialnya. Dalam praktiknya, Badan Kehutanan Jepang mengakui produk kayu dari perusahaan seperti Hanwa—pemegang saham BJA—hanya berdasarkan dokumen tersebut.
Sementara itu, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri memang mensyaratkan prinsip keberlanjutan bagi operator pembangkit biomassa, namun tidak berani menentang penilaian Badan Kehutanan.
Junichi menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan rendahnya prioritas pemerintah Jepang terhadap isu deforestasi di luar negeri. “Jika produk dianggap sah berdasarkan dokumen dari negara asal, pemerintah Jepang tidak melangkah lebih jauh,” ujarnya
Ia menekankan bahwa SVLK hanya menjamin legalitas, bukan keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan informasi langsung kepada pemerintah Jepang dan Korea agar mereka memahami bahwa energi “hijau” mereka mungkin berasal dari kehancuran ekosistem di luar negeri.
“Pemerintah Jepang dan Korea Selatan seharusnya memperketat pedoman keberlanjutan dan ketertelusuran biomassa,” tambah Junichi Mishiba.
Selain itu, Junichi menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan energi biomassa di Jepang. Ia menilai bahwa promosi pembangkit listrik biomassa melalui skema FIT yang diberi label “ramah lingkungan” justru bersifat kontraproduktif, karena mendorong penebangan serta konversi hutan alam Indonesia yang kaya keanekaragaman hayati.
“Skema FIT dibiayai oleh publik melalui tambahan biaya pada tagihan listrik. Karena itu, pemerintah Jepang dan perusahaan terkait perlu meninjau kembali kebijakan ini,” tegasnya.
Investasi “Hijau” dengan Korporasi “Kotor”
Bukan hanya mengimpor, Jepang dan Korea Selatan rupanya juga ikut terlibat langsung dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan yang menebang hutan alam di Pohuwato. Misalnya, Hanwa Co. Ltd., perusahaan perdagangan global asal Jepang berinvestasi sebesar 20 persen kepemilikan di pabrik pelet BJA yang dapat memproduksi 900 ribu ton per tahun.
Dengan kepemilikan saham itu, Hanwa Co. Ltd mengklaim itu adalah investasi “hijau” yang akan berkontribusi pada kebijakan dekarbonisasi negaranya. Selain itu, perusahaan tersebut juga mengekspor pelet kayu dari BJA ke Korea Selatan dengan klaim yang sama.
Selain berinvestasi di BJA, Hanwa Co. Ltd. juga menjalin kemitraan dalam pengembangan “biofuels” bersama Provident Group, sebuah konglomerasi yang dikendalikan oleh Winato Kartono, Edwin Soeryadjaya, Garibaldi Thohir, dan Sandiaga Uno. Provident Group rupanya memiliki afiliasi dengan BTL, IGL, dan BJA.
Hal ini memperkuat laporan Mighty Earth pada akhir 2023 mencatat perusahaan-perusahaan Jepang terlibat dalam 49 proyek co-firing biomassa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pohuwato.
Pada awal November lalu, FoE bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia, termasuk FWI, mengirimkan surat kepada Hanwa Co., Ltd. untuk mendesak penghentian impor pelet kayu yang dinilai mendorong terjadinya deforestasi di Indonesia.
“Kami juga menuntut adanya kebijakan impor yang transparan serta penyelidikan menyeluruh terkait aspek keberlanjutan dan hak asasi manusia dalam rantai pasok pelet kayu yang diimpor dari Indonesia,” ucap Junichi.
Namun, di balik aktivitas ekspor pelet kayu dan investasi itu, muncul sejumlah perusahaan yang terhubung dengan jaringan bisnis besar di Jakarta. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), tiga perusahaan utama yang beroperasi di Pohuwato—BTL, IGL, dan BJA—terafiliasi dengan konglomerasi lama di sektor kehutanan dan energi.
Jaringan kepemilikan perusahaan ini berlapis-lapis. Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, bos besar Adaro Group, tercatat sebagai pemilik PT Energi Hijau Bersama, pemegang saham terbesar BJA dengan porsi 43 persen. Perusahaan ini juga memiliki saham di PT Sekawan Alam Lestari, pemilik 33 persen saham BJA.
Di belakang Energi Hijau Bersama berdiri PT Mentari Anugerah Sejahtera, yang mayoritas sahamnya dikuasai PT Provident Capital Partners, perusahaan berbasis di Singapura dan terafiliasi dengan Merdeka Copper Gold—kelompok usaha yang juga berada di bawah kendali Boy Thohir.
Jejak keterkaitan ini makin kuat dengan munculnya nama Albert Saputro, Presiden Direktur Merdeka Copper Gold sekaligus petinggi Saratoga Investama Sedaya—perusahaan investasi milik Edwin Soeryadjaya, Sandiaga Uno, dan Boy Thohir. Ia juga duduk sebagai Komisaris BJA.

Nama Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, juga muncul dalam struktur kepemilikan Energi Hijau Bersama. Trenggono memiliki hubungan bisnis dengan Adaro melalui PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, perusahaan menara telekomunikasi yang ia komisaris sebelum menjabat menteri.
Adapun struktur dua perusahaan pemegang konsesi hutan di Pohuwato, IGL dan BTL, juga serupa. Keduanya dikendalikan oleh PT Buana Pratama Cipta, yang dimiliki oleh PT Reka Varia Tara. Meski tidak tercatat di AHU, laporan Betahita.id menyebut, perusahaan itu pernah tercatat dalam laporan keuangan Merdeka Copper Gold tahun 2015, sebagai penerima hak atas proyek tambang Tujuh Bukit di Banyuwangi.
Di antara para komisaris dan pemegang sahamnya, muncul pula nama Andy Kelana, pengacara senior yang memiliki posisi strategis di berbagai perusahaan besar, termasuk PT Multistrada Arah Sarana Tbk, PT Paiton Energy, serta PT American Express Indonesia. Ia kini menjabat Presiden Komisaris PT BJA.
Keterlibatan nama-nama besar ini memperlihatkan bahwa proyek biomassa di Pohuwato bukan sekadar inisiatif energi bersih, melainkan bagian dari konglomerasi kepentingan bisnis dan politik. Jaringan kepemilikan ini menggambarkan di balik bendera “energi hijau”, berdiri konglomerasi yang sama—para pemain lama sektor batu bara, tambang, dan kehutanan.
Amelya Reza Oktaviani, Manajer Program Bioenergi Trend Asia, membenarkan, pelaku usaha yang mengembangkan HTE dan memasok biomassa kayu ke PLTU sejatinya adalah pemain lama di industri yang kotor. Fakta ini tercatat dalam riset Trend Asia, “Penanggguk Cuan Transisi Energi”, yang diterbitkan tahun lalu.
“Korporasi pemilik modal besar dan pengusaha dengan relasi kuat tetap mendominasi bisnis transisi energi,” ujarnya.
Menurut Amelya, pelaku usaha HTE yang menyuplai bahan baku co-firing biomassa ke PLTU umumnya terafiliasi dengan konglomerat yang dulu menguasai lahan dan bisnis kehutanan. Perusahaan yang sebelumnya memasok batu bara ke PLTU kini merambah suplai kayu untuk PLN.
Korporasi-korporasi inilah yang paling diuntungkan dari program co-firing biomassa. Selain kapasitasnya, mereka mampu menutup akses bagi pihak lain dan memastikan insentif pemerintah mengalir penuh. Sebagian besar pelaku usaha HTE ini memiliki sejarah panjang: bergerak dari industri kayu, kelapa sawit, hingga batu bara.
Kini, kata Amelya, konglomerat-konglomerat lama di industri kotor itu mengikuti tren energi baru, lalu mengklaim diri sebagai penyokong transisi energi terbarukan di Indonesia.
“Rata-rata korporasi yang terlibat proyek HTE ini juga memiliki masalah lama terkait sosial dan lingkungan hidup,” pungkas Amelya.
Perusahaan Bungkam
Sejak 5 November, saya melayangkan surat konfirmasi kepada tiga perusahaan—BTL, IGL, dan BJA—untuk meminta jawaban atas serangkaian tudingan terkait krisis ekologis yang diduga dipicu aktivitas mereka. Termasuk di dalamnya dugaan jejaring kepemilikan yang beririsan dengan konglomerasi batu bara, pertambangan, dan kehutanan.
Hingga dua pekan berselang, tak satu pun dari ketiga perusahaan itu bersedia menanggapi. Mereka memilih bungkam. Keputusan itu dibenarkan oleh Berliana Elisabeth, Public Relations BJA Group.
“Mohon maaf, setelah berkoordinasi dengan manajemen klien, mereka memutuskan untuk tidak memberikan jawaban,” tulis Berliana melalui pesan WhatsApp pada Rabu (19/11/2025).
Saya juga menghubungi Zunaidi, Direktur BTL, IGL, dan BJA, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga laporan ini disusun, ia belum memberikan penjelasan.
Di sisi lain, Nasruddin, Kepala Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan Dinas LHK Gorontalo, mengaku belum pernah memeriksa langsung lokasi konsesi BTL dan IGL untuk memastikan proses penebangan hutan alam. Ia hanya turun ke beberapa kecamatan di Pohuwato yang mengalami krisis air bersih.
Nasruddin mengakui bahwa sejumlah kecamatan memang kekurangan air bersih karena sumber air menjadi keruh. Namun ia menilai persoalan itu lebih disebabkan oleh teknologi PDAM Pohuwato yang sudah usang. Ia juga menunjuk aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dengan alat berat di hulu sungai sebagai penyumbang utama kerusakan sumber air.
Tentang kemungkinan keterkaitan krisis air bersih dengan aktivitas BTL dan IGL, Nasruddin berhati-hati. Ia mengaku memiliki kecurigaan, tetapi belum bisa memastikan. “Kita perlu lihat secara spasial apakah krisis air itu juga dipicu oleh aktivitas BTL dan IGL atau tidak,” katanya.
Begitu pula soal banjir yang makin sering terjadi setelah perusahaan beroperasi. Nasruddin menekankan perlunya analisis spasial yang memetakan lokasi banjir, daerah aliran sungai (DAS), serta titik kegiatan perusahaan. Tanpa itu, ia belum mau menyimpulkan.
“Biasanya banjir dipengaruhi faktor alam juga, seperti curah hujan tinggi. Harus dilihat secara detail,” ujarnya.
Nasruddin memastikan, jika nanti terbukti aktivitas perusahaan memicu banjir, Dinas LHK akan menjatuhkan sanksi tegas—dari administrasi hingga pencabutan izin. Namun sejauh ini, belum ada laporan resmi yang masuk soal keterlibatan perusahaan dalam banjir.
Nasruddin juga menyebut dokumen Amdal atau izin lingkungan BTL dan IGL telah diubah; keduanya tidak lagi menggunakan Amdal perkebunan sawit dan kini beralih ke skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Adapun Amdal BJA, kata dia, menjadi satu paket dengan BTL karena pabriknya dibangun di dalam kawasan konsesi BTL.

Paradoks Energi
Cerita tentang ambisi hijau Jepang dan Korea Selatan yang memicu petaka di Pohuwato menggambarkan sebuah paradoks energi global: negara-negara maju berlomba menekan emisi karbon di dalam negeri, tetapi pada saat yang sama mendorong deforestasi di negara berkembang, memicu bencana ekologis yang serius.
Di Seoul dan Tokyo, para pejabat pemerintah dengan bangga memamerkan laporan penurunan emisi serta capaian energi terbarukan. Namun di Pohuwato, Hasan Lakoro hingga Ratna Ismail hidup dalam bayang-bayang bencana ekologis yang bisa kembali merenggut nyawa saudara mereka—bahkan nyawa mereka sendiri.
“Katanya untuk menyelamatkan bumi,” ujar Hasan dengan pelan. “Tapi bumi kami justru rusak, hutan banyak yang hilang, dan kami hidup dalam ketakutan akan bencana yang bisa terulang,” sambung Hasan.
Sore itu, dari tenda darurat yang telah ia tempati hampir tiga bulan, Hasan kembali menatap tepi sungai yang berubah keruh. Di seberang lautan, kapal kargo bermuatan pelet kayu dari Pohuwato bersandar di sebuah pelabuhan di Jepang, disambut sebagai bagian dari “transisi energi bersih”.
Ambisi hijau Jepang dan Korea Selatan mungkin berhasil menekan emisi karbon di negara masing-masing. Tetapi di Gorontalo, harga yang harus dibayar sangat mahal: hutan hilang, air tercemar, dan nyawa melayang.
“Kalau ini yang disebut hijau,” kata Hasan, suaranya bergetar, “mungkin warna hijau itu sudah bercampur darah.”
Liputan ini didukung program fellowship Transisi Energi Berkeadilan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).
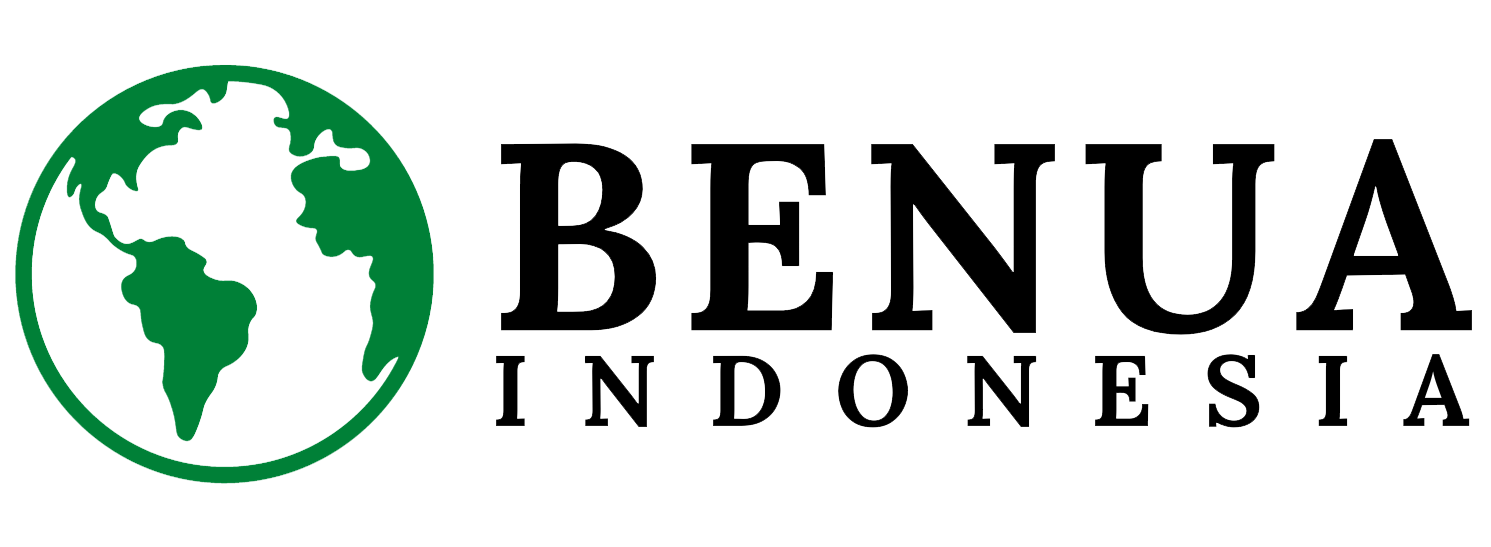



















Leave a Reply
View Comments