- Masyarakat Adat Moa, sudah mendapatkan penetapan hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hanya saja, usulan dan penetapan jauh beda. Usulan penetapan hutan adat 7.738 hektar, realisasi hanya 1.484 hektar.
- Sejak 2017, pemerintah desa, lembaga adat yang dibantu Karsa Institute dan Kemitraan-Partnership mengusulkan penetapan hutan adat kepada KLHK untuk Masyarakat Adat Moa. Wilayah adat itu ada di Desa Moa, Kecamatan Kulawi Selatan seluas 7.738 hektar, masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dan hutan lindung.
- Komunitas Adat Topo Uma diarahkan untuk hidup menetap dan dipindahkan ke perkampungan baru di wilayah yang disebut moa. Nama moa berasal dari kata moahu secara harfiah berarti berburu. Sebutan moa diambil dari kebiasaan komunitas adat di Boku yang suka berburu saat itu.
- Pada level Pemerintah Sigi, Masyarakat Adat Moa sudah dapatkan pengakuan berdasarkan Peraturan Perda Sigi pada 2014 soal pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Daud Rori agak sedikit kecewa saat menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan Hutan Adat untuk masyarakat adat moa di Desa Moa, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng). SK yang diterbitkan pada 10 September 2021 itu hanya memberikan 1.484 hektar Hutan Adat dari 7.738 hektar yang diusulkan. Daud bilang, luasan yang diberikan itu cukup sedikit bagi masyarakat adat moa, dan itu akan mengancam masa depan keberlangsungan hidup generasinya.
“1.484 hektar ini cukup sedikit bagi masyarakat adat moa, karena jumlah penduduk kami semakin hari semakin bertambah. Ini akan mengancam ruang hidup masa depan anak-anak dan cucu-cucu kami nanti. Hutan adalah sumber kehidupan kami,” kata Daud Rori, Wakil Ketua Lembaga Adat Moa kepada Mongabay, pada awal Juli lalu.
Sejak 2017, Pemerintah Desa, Lembaga Adat yang dibantu oleh Karsa institute dan Kemitraan-Partnership mengusulkan pengakuan Hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk masyarakat adat moa. Wilayah adat yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Hutan Adat berada wilayah di Desa Moa, Kecamatan Kulawi Selatan dengan seluas 7.738 hektar yang masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dan Hutan Lindung (HL).
Sebenarnya, langka pengusulan hutan adat itu diambil untuk meminimalisir ketimpangan dan konflik agraria yang disebabkan begitu besarnya dominasi Negara terhadap penguasaan dan kontrol atas sumber daya alam di dalam kawasan hutan. Pasalnya, tata guna dan sistem penguasaan tanah oleh komunitas-komunitas adat termasuk masyarakat adat moa, berubah secara drastis akibat kebijakan Negara yang merampas lahan mereka untuk dijadikan kawasan hutan dan konservasi.
Daud bilang, masyarakat tidak dapat lagi dengan leluasa mengakses wilayah-wilayah adatnya bahkan di lahan permukiman dan juga lahan-lahan pertanian, dan perkebunan yang sejak berabad-abad lalu sudah mereka kuasai dan kelola. Ketimpangan agraria ini pun dapat berpotensi munculnya konflik-konflik agraria antara komunitas-komunitas adat dengan Negara. Olehnya, kata Daud, masyarakat adat moa mengusulkan hutan adat sebagai solusi persoalan agraria yang tengah mereka hadapi.
Terlebih, masyarakat adat moa juga sudah mendapatkan pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.
Jugaerta Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-521 tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi. Sayangnya, dari proses pengusulan hingga penetapan hutan adat membutuhkan waktu sekitar empat tahun, itu pun luasan yang diberikan sangat jauh dari luasan yang diusulkan.

“Kami mengusulkan sejak 2017, nanti pada akhir 2021 baru ada penetapan hukum adat. Ada 4 tahun kami memperjuangan adanya penetapan hutan adat, dan selama itu Negara seperti mempersulit, serta luasan yang diberikan cukup kecil,” jelas Daud
Padahal, bagi masyarakat adat moa, hutan merupakan urat nadi dan menjadi sumber kehidupan turun temurun sejak dari nenek moyangnya. Mereka mempunyai ikatan emosional dan kultural yang kuat terhadap hutan, dengan kata lain hutan adalah bagian integral dari kehidupan masyarakatnya.
Hampir seluruh sumber daya di hutan baik kayu maupun non kayu memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan orang Moa. Kegiatan mereka di dalam hutan pun sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu sebelum adanya Negara.
Masyarakat adat moa merupakan komunitas adat Topo Uma, salah satu suku asli Kulawi yang berbahasa uma. Berdasarkan catatan Kaudern, Walter. 1925: Ethnographical studies in Celebes: Results of the author’s expedition to Celebes 1917–1920, komunitas adat Topo Uma sebelumnya tinggal dan menetap di sebuah lembah di sekitar pegunungan Boku dan Haluboko di tepian sungai lariang (koro) sudah sejak lama.
Saat itu, mereka memanfaatkan lembah dan pegunungan di sekitar sebagai ”huaka” atau ruang (kelola) hidup dengan berkebun ladang jenis padi lokal (pae konihi), mengumpulkan umbut rotan dan kacang hutan (meramu) dan berburu.
Sekitar tahun 1920-an, pemerintahan kolonial Belanda merelokasi masyarakat yang hidup nomaden dan terpencar-pencar di sekitar Boku dan Haluboko untuk memudahkan jalannya roda pemerintahan saat itu. Hal itu juga bersamaan dengan masuknya misionaris Kristen Protestan-Bala Keselamatan di seluruh wilayah Pipikoro

Komunitas adat Topo Uma diarahkan untuk hidup secara menetap dan dipindahkan ke perkampungan baru di wilayah yang disebut Moa. Nama Moa berasal dari kata moahu yang secara harfiah berarti berburu. Sebutan moa diambil dari kebiasaan komunitas adat di wilayah Boku yang memang suka berburu saat itu. Boku sendiri saat ini tidak lagi dihuni sebagai permukiman penduduk dan dikenal sebagai kampung tua orang Moa. Komunitas adat Topo Uma ini pun kerap disebut masyarakat adat moa.
Pada masa kolonial Belanda, masyarakat adat moa juga masih hidup dengan sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh seorang maradika. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan tradisional Komunitas adat Topo Uma berganti menjadi pemerintahan kampung yang dipimpin oleh seorang kepala kampung disebut totua ngata. Pada zaman orde baru, pemerintahan kampung berganti menjadi pemerintahan desa, dan Kampung Moa berganti menjadi Desa Moa yang dipimpin oleh seorang kepala desa hingga saat ini.
Masyarakat adat moa merupakan masyarakat agraris, dimana tanah dan lahan sangat penting untuk bercocok tanam dan mengembangkan kegiatan budi daya pertanian sebagai sumber perekonomian dan pemenuhan kebutuhan hidup. Ada sekitar 97 persen warga masyarakat adat moa berprofesi sebagai petani yang mengolah tanaman kakao, jagung, dan kopi yang sistem penanaman dan perawatannya tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Selain itu, komoditi lain yang dibudidayakan adalah padi ladang, padi sawah, kemiri dan tanaman palawija.
Ada juga beberapa kebutuhan hidup diperoleh dari hutan seperti kayu (kau), rotan (ui ), bambu (walo), pandan hutan (naho), tumbuhan obat-obatan (pakuli), wangi-wangian (wongi-wongi), enau (baru), nibung (wanga), umbut (uwu) dan lain-lain. Secara filosofi masyarakat hukum adat Topo Uma secara umum dikenal dengan penyebutan hintuwu (yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia), katuwuan (yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam) dan petukua (mengatur hubungan dengan sang pencipta).
Sejarah itulah yang membuat masyarakat adat moa memiliki pemaknaan yang mendalam terkait interaksinya dengan hutan. Menurut mereka, hutan tidak hanya dimaknai sebagai sumber pemenuhan kebutuhan jasmani saja, namun lebih dari itu, hutan juga menjadi inspirasi budaya yang melahirkan ikatan-ikatan spiritual dan religi. Pemaknaan ini melahirkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang kemudian menjadi budaya dan tradisi yang membentuk jati diri komunitas adat dan orang moa sebagai petani.
Mereka mengelola hutan sebagai lahan pertanian dan kebun dengan berbagai jenis tanaman pangan dan juga tanaman komoditi untuk kebutuhan ekonomi. Lahan-lahan pertanian dan kebun yang dikelola merupakan wilayah-wilayah adat sebagai warisan turun temurun dari nenek moyang Topo Uma. Komunitas adat Topo Uma di Desa Moa memiliki wilayah adat seluas kurang lebih 34.485 hektar dengan batas-batas wilayah yang terhubung dengan lintas desa, kecamatan, kabupaten, bahkan hingga provinsi.
Namun sejak tahun 1993, wilayah-wilayah adat komunitas adat Topo Uma ini ditetapkan sebagai bagian dari kawasan hutan negara dengan fungsi konservasi. Dibentuknya Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 593/Kpts-II/1993 dan Hutan Lindung yang masuk dalam Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) unit VIII, SK Menteri Kehutanan Nomor SK.79/Menhut-II/ Tahun 2010, membuat komunitas adat Topo Uma kehilangan akses atas wilayah-wilayah adatnya. Mereka terbelenggu dengan hutan negara.

Dampak Penguasaan Hutan Negara
TNLL yang terletak sekitar 60 kilometer selatan kota Palu serta berada di selatan Kabupaten Sigi dan bagian barat Kabupaten Poso ini awalnya memiliki luas luas 229.000 hektar yang ditetapkan pada tahun 1993. Pada tahun 1999 dilakukan pengukuran dan tata batas definitif melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.464/kpts-II/1999 tanggal 28 Juli 1999. Saat itu, luas TNLL secara resmi ditetapkan sebesar 217.991,18 hektar.
Selanjutnya pada tahun 2014 telah disahkan perubahan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang berimplikasi pada perubahan kawasan hutan termasuk TNLL. Perubahan tersebut telah diakomodir melalui Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. Alhasil, pada tanggal 29 September 2014, luas TNLL kembali ditetapkan menjadi 215.733,70 hektar.
Daud bilang, penetapan sepihak pemerintah yang mengklaim wilayah-wilayah adat Topo Uma di Desa Moa sebagai kawasan hutan Negara, telah membuat ketimpangan dan berdampak pada pola pemanfaatan lahan untuk wilayah kelola masyarakat adat.
Ruang penghidupan mereka terhimpit karena keterbatasan akses atas hutan dan lahan yang dapat dikelola untuk pertanian ladang serta kebun. Katanya, semakin sempitnya wilayah kelola mempengaruhi pola produksi dan konsumsi mereka dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.
“Sejak ada penguasaan hutan yang dilakukan Negara, kita tidak bisa melakukan aktivitas lebih di wilayah adat kita. Ruang kelola untuk penghidupan kita semakin terhimpit dengan semakin bertambahnya populasi masyarakat adat moa,” jelas Daud
Berdasarkan catatan Karsa Institute, lembaga yang mendampingi masyarakat adat moa menjelaskan, sebelum ada TNLL, total luas wilayah adat Moa sebesar 34.530 hektar pada 1900- 1981. Penggunaan lahan pada masa itu dimanfaatkan sebagai tempat berburu, berkebun ladang, mengambil kayu dan rotan untuk kebutuhan rumah tangga. Ada juga lahan yang dimanfaatkan sebagai pampa oleh perempuan adat, untuk berkebun sayur-sayuran seperti sawi, kacang-kacangan, jagung, cabe, dan bumbu dapur.
Tahun 1955-1960 sebahagian kawasan hutan bekas kebun padi ladang dimanfaatkan untuk berkebun kopi. Saat itu merupakan merupakan masa kejayaan masyarakat adat moa karena menjadi salah satu desa penyuplai kopi terbesar di Sulawesi Tengah. Pada tahun 1990-1997 masyarakat mulai menanam kakao yang dibudidayakan secara tradisional berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat dengan tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia.
Sementara untuk kebutuhan subsisten yang bersumber dari hasil bonea atau kebun padi ladang dan pampa (wilayah kelola perempuan adat) semuanya tersedia di komunitas. Bahkan pada era 1970-an, masyarakat moa juga salah satu penghasil beras ladang terbaik di Sulteng. Sedangkan kampung tua Boku dan Haluboko dijadikan sebagai tempat ritual acara-acara religius dan tempat ziarah makam-makam tua yang dianggap sebagai leluhur masyarakat adat moa.
Namun, setelah ditetapkan menjadi TNLL, hampir 85% wilayah adat masyarakat adat moa masuk dalam kawasan hutan Negara. Penetapan itu pun tidak pernah diketahui atau disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat adat Moa tidak mengetahui kalau sebagian besar dari wilayah kelola mereka masuk dalam kawasan hutan. Bahkan, mereka kerap mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari petugas kehutanan saat mengambil rotan.

Rotan masyarakat dipotong lalu dibakar dan kejadian ini selalu berulang-ulang jika ada rotan yang didapat. Masyarakat tidak dapat lagi mengambil kopi, karena area tersebut masuk dalam kawasan hutan. Banyak kebun kopi yang ditebang oleh petugas saat melakukan patroli. Intimidasi yang dilakukan oleh petugas kehutanan kepada masyarakat lokal sangat masif, dengan dalih sedang menjalankan tugas Negara.
“Jika ada yang melawan maka masyarakat dianggap menghambat pembangunan, dan dicap sebagai perusak hutan. Tindakan seperti ini juga dirasakan hampir semua desa yang berkonflik dengan kawasan hutan, dan konservasi,” Kata Desmon Mantaili, Program Manager Karsa Institute. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkantor di Kota Palu ini sudah hampir satu dekade mendampingi masyarakat adat moa untuk memperjuangkan hutan adat mereka.
Selain itu, desa yang berada di ujung selatan Kabupaten Sigi tersebut sampai hari ini tidak memiliki akses jalan yang memadai, karena letak geografisnya terpencil di wilayah perbukitan yang berbatasan dengan TNLL. Jaraknya, sekitar 24 km dari Gimpu, ibu kota kecamatan Kulawi Selatan, dan 120 km dari pusat Kota Palu.
Dari Gimpu, modal transportasi yang dapat digunakan hanya sepeda motor dengan perjalanan sekitar sekitar tiga jam menyusuri jalan setapak di tepi jurang terjal di pinggiran sungai lariang-sungai terpanjang di Sulawesi.
Kondisi geografis yang sulit diakses karena status kawasan hutan dan taman nasional di sekitarnya membuat desa yang memiliki jumlah penduduk 245 jiwa ini masih minim infrastruktur dan fasilitas layanan publik. Terutama untuk sektor pendidikan karena hanya Sekolah Dasar yang di desa ini.
Selain sarana yang terbatas, jumlah tenaga medis dan tenaga pendidik juga masih belum mencukupi untuk dapat melayani kebutuhan seluruh warga desa. Desmon bilang, semua itu karena dampak dari penguasaan hutan oleh Negara.
Padahal, kata Desmon, masyarakat adat moa memiliki konsep pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal yang dibagi dalam beberapa tingkatan atau kategori (zona). Misalnya; zona Pongataa, wilayah yang dicadangkan untuk permukiman; Polidaa, areal untuk persawahan atau lahan untuk budidaya padi sawah, beternak itik; Pampa kebun campur tempat budidaya tanaman pangan dan tanaman musiman seperti palawija dan tanaman hortikultura; serta Pocoklat, kebun tanaman keras dengan tanaman utama berupa kakao.
Ada juga zona Pokopia, kebun tanaman keras dengan tanaman utama berupa kopi: Lamara, lokasi penggembalaan kerbau dan sapi umumnya berupa hutan sekunder; Bonea, ladang yang ditanami padi, jagung, sayur-sayuran, dan rempah-rempah; Bilingkia, bekas ladang yang berusia dibawah 1 tahun, permukaan lahan ditutupi oleh tumbuhan herba berumur pendek, alang-alang, dan sedikit belukar; serta Oma Bou, bekas ladang berusia antara 1-2 tahun yang mana dominasi alang- alang dipermukaan tanah mulai digantikan oleh tumbuhan berkayu berupa semak, belukar dan anakan pohon kecil.
Selain itu, ada juga Oma Nete, bekas ladang berusia 3-10 tahun yang didominasi pohon-pohon kayu ukuran kecil, menggantikan dominasi semak dan belukar; Oma tua, bekas ladang berusia diatas 10 tahun, anakan pohon besar (batang) tumbuh melampaui pepohonan kecil sehingga mulai membentuk strata pepohonan; Pahawa Pongko, hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan dengan umur 25 tahun keatas yang sudah hampir menyerupai hutan sekunder semi hutan primer (Peponurua), karena pohon-pohonnya sudah tumbuh besar

Tak hanya itu, ada juga zona Ko’olo, kawasan hutan larangan yang dicagarkan karena pertimbangan ekologis seperti daerah aliran sungai, mata air, tebing yang rawan longsor, dan menjadi tempat-tempat bersejarah/keramat yang memiliki nilai spiritual dan budaya; dan Ponulu, hutan primer yang terdapat di dekat pemukiman atau di sekitar lahan-lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lokasi berburu serta mengambil rotan, kayu bahan bangunan (rumah), damar, obat-obatan dan hasil hutan lainnya.
Bukan hanya itu, ada juga zona Wana, kawasan hutan primer terletak jauh dari pemukiman atau dari lahan-lahan pertanian yang hanya digunakan sebagai tempat berburu, mengambil getah damar atau gaharu, mengambil rotan, dan tumbuhan obat meski dalam skala yang terbatas; serta zona Wanangkiki, kawasan hutan pegunungan atas terletak di puncak gunung tinggi jauh dari pemukiman penduduk, ditumbuhi pohon berbatang keras, berukuran kerdil. Batang, dahan, daun pepohonan dan lantai hutan diselimuti lumut.
Menariknya, masyarakat adat moa menggunakan metode perladangan gilir balik secara integral. Artinya, setiap tanah atau lahan yang sudah selesai dipanen hasilnya, akan diistirahatkan dulu. Istilah ini berbeda dengan tanah yang ditelantarkan. Katanya, bagi masyarakat adat moa, jika lahan tidak diistirahatkan setelah dilakukan panen, maka akan menyebabkan tanahnya akan menjadi kritis atau rusak. Konsep itu merupakan warisan bertani dari leluhur orang moa.
“Semua zona-zona ini, ada aturan, larangan, hingga sanksi yang dibuat oleh masyarakat adat moa, jika ada yang melanggarnya. Sebenarnya, masyarakat adat moa ini lebih ketat menjaga hutan ketimbang dengan petugas kehutanan atau polisi hutan,” kata Desmon
Sayangnya, kata Desmon, masyarakat adat moa tidak dilibatkan untuk ikut menjaga hutan. Alhasil, banyak masyarakat dari luar desa secara diam-diam mengambil hasil hutan seperti kayu, rotan, gaharu dan damar di wilayah Moa, sementara masyarakat adat menjadi penonton dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pancodo ngata atau penjaga hutan yang diberikan kuasa oleh lembaga adat untuk melakukan fungsi patroli terhadap hutan menjadi melemah.
Arma Janti Massang, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menepis anggapan itu. Katanya, balai sangat paham dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat moa dalam pengelolaan hutan. Adapun luasan yang ditetapkan berbeda dengan luasan yang diusulkan merupakan bagian dari petimbangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena taman nasional dikelola berdasarkan sistem zonasi. Ia berdalil, sistem zonasi itu yang disesuaikan dengan zona-zona kearifan lokal pengelolaan hutan masyarakat adat moa.
Meski begitu, Ia sedikit kecewa dengan SK penetapan hutan adat untuk masyarakat adat moa yang diterbitkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK. Pasalnya, dalam SK itu tidak ada tembusan ke Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan ke BBTNLL. Padahal, BBTNLL menjadi bagian dalam tim terpadu dalam melakukan validasi dan verifikasi administrasi untuk wilayah yang diusulkan menjadi hutan adat, serta kawasan mereka yang dilepas.
Disisi lain, katanya, BBTNLL diwajibkan melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas lembaga adat dan serta komunitas adat Topo Uma di Moa dengan membangun kolaborasi berbagai pihak. Padahal, kalau sudah bicara masyarakat hutan adat sudah bukan kewajiban BBTNLL untuk melakukan pemberdayaan. Walaupun begitu, pihaknya tetap akan mengamankan kebijakan pimpinan.
“Lebih baik masyarakat kerjakan dulu apa yang ada misalnya melakukan tata batas, walaupun luasan yang diberikan tidak sesuai dengan luasan yang diusulkan,” kata Arma Janti Massang kepada Mongabay, awal Juli lalu.
Tulisan ini pertama kali diterbitkan di situs Mongabay Indonesia dalam versi sudah sunting. Untuk membacanya silahkan klik di sini.
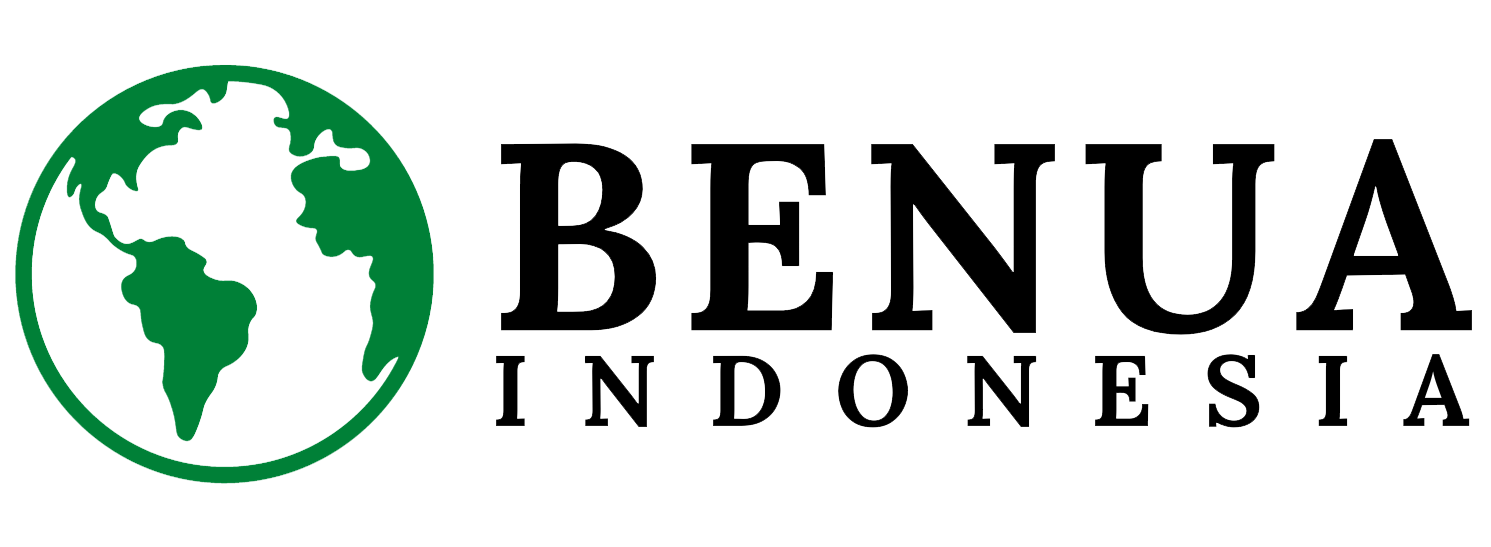









Leave a Reply
View Comments