Saat air, udara, dan tanah menjadi rebutan, kita dipaksa bertanya akan seberapa siap dunia menghadapi perang tanpa peluru?
Bayangkan dunia di mana bencana alam bukan lagi kejadian luar biasa, tapi rutinitas yang menandai setiap pergantian musim. Hujan ekstrem mengguyur tanpa jeda, sementara di belahan lain bumi retak oleh kekeringan panjang. Petani kehilangan ladang, nelayan kehilangan lautnya, dan masyarakat kehilangan rumah mereka karena banjir, badai, serta kebakaran hutan yang makin sering datang tanpa ampun.
Inilah kenyataan baru yang perlahan menggantikan definisi “normal” kita. Di titik ini, perubahan iklim berhenti menjadi isu lingkungan dan berubah menjadi ancaman nyata bagi keamanan manusia dan stabilitas global. Ia bukan lagi persoalan masa depan, tetapi krisis hari ini, krisis yang menguji kemampuan negara, solidaritas antarbangsa, dan daya tahan kemanusiaan.
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2023 memperingatkan bahwa suhu global telah meningkat sekitar 1,2°C dibandingkan era pra-industri. Angka yang tampak kecil, tapi cukup untuk mengubah peta kehidupan di bumi karena dampaknya yang berhasil menurunkan hasil panen, memicu kelangkaan air, memperparah migrasi massal, dan mengguncang stabilitas politik di berbagai kawasan.
Dunia kini tengah menghadapi perang baru, bukan karena peluru dan senjata, tetapi karena perebutan sumber daya paling dasar untuk bertahan hidup.
Hubungan antara perubahan iklim dan konflik bukan teori semata. Sejarah sudah berulang kali menunjukkan bahwa bencana alam dapat menjadi bahan bakar bagi ketegangan sosial dan politik.
Baca juga: Janji Iklim Indonesia Alami Kemunduran?
Sebelum perang saudara Suriah meletus pada 2011, negara itu mengalami kekeringan paling parah dalam sejarah modernnya. Selama hampir empat tahun, hujan tak kunjung turun, ladang mengering, dan lebih dari 1,5 juta petani terpaksa meninggalkan desa mereka menuju kota-kota besar untuk mencari penghidupan.
Migrasi besar-besaran itu memicu tekanan ekonomi, lonjakan harga pangan, dan ketimpangan sosial yang memburuk yang hingga akhirnya percikan kecil ketidakpuasan berubah menjadi kobaran konflik yang melibatkan aktor internasional.
Fenomena serupa terjadi di kawasan Sahel, Afrika. Kekeringan ekstrem memaksa petani dan penggembala bersaing memperebutkan sumber air yang kian menipis. Perebutan lahan yang awalnya bersifat lokal berkembang menjadi konflik etnis dan agama yang kompleks.
Situasi itu dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata seperti Boko Haram, yang merekrut warga putus asa sebagai cara bertahan hidup. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), lebih dari 40% konflik internal dalam 60 tahun terakhir berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, termasuk air dan lahan.
Artinya, perubahan iklim bukan penyebab tunggal perang, tetapi ia adalah katalis yang berperan dalam mempercepat, memperluas, dan memperdalam krisis yang telah ada. Dalam konteks global, ini berarti dunia kini menghadapi bentuk baru ancaman keamanan. perang tanpa peluru, di mana panas bumi, kekeringan, dan kelangkaan sumber daya menggantikan senjata dan misil sebagai pemicu kekacauan.

Dari Pangan ke Migrasi, Krisis yang Menular
Dampak perubahan iklim tidak berhenti pada kekeringan atau badai. Ia menjalar jauh melampaui batas geografis dan sektor, menembus ranah pangan, ekonomi, hingga migrasi manusia. Inilah yang membuatnya berbahaya karena krisis iklim bukan hanya urusan cuaca, melainkan rantai sebab-akibat yang bisa mengguncang fondasi kehidupan modern.
PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2050, produktivitas pertanian global bisa turun hingga 30%, terutama di negara-negara berkembang yang masih bergantung pada sektor agraria. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan keras bahwa satu musim gagal panen dapat berarti lonjakan harga, kelaparan, dan gejolak sosial.
Ketika sawah mengering dan hasil tangkapan laut menurun, dampaknya tidak berhenti di desa, tetapi menjalar ke kota, ke pasar, hingga ke meja makan setiap keluarga.
Krisis pangan global tahun 2022 menjadi contoh nyata bagaimana perubahan iklim memperparah konflik yang sudah ada. Ketika perang Rusia–Ukraina memutus pasokan gandum dunia, gelombang panas ekstrem di India dan Pakistan menghancurkan panen yang tersisa.
Akibatnya, harga pangan global melonjak tajam, memicu protes di Sri Lanka, Tunisia, hingga Kenya. Peristiwa itu menunjukkan bahwa satu guncangan di satu wilayah dapat menjalar ke seluruh dunia, seperti domino yang jatuh satu per satu.
Lebih jauh lagi, perubahan iklim juga menggerakkan manusia dalam skala besar. Laporan World Bank tahun 2021 memprediksi lebih dari 200 juta orang akan menjadi pengungsi iklim pada tahun 2050, terutama di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Migrasi besar-besaran ini akan menciptakan tekanan baru terhadap sumber daya, memperbesar ketimpangan, dan pada akhirnya mengancam stabilitas politik antarnegara.
Baca juga: Dampak Kemajuan Industri China Terhadap Perubahan Iklim Dunia
Dengan kata lain, perubahan iklim adalah katalis yang mempercepat krisis yang sudah ada, ia tidak menciptakan konflik dari nol, tetapi memperdalam luka yang belum sembuh. Dan ketika ketegangan sosial, ekonomi, dan politik bertemu dalam satu titik, yang lahir bukan hanya penderitaan, tapi potensi perang baru dalam bentuk yang lebih sunyi dan kompleks.
Krisis ini memperlihatkan celah besar dalam sistem global kita dimana dunia berlari cepat menghadapi ancaman militer, tapi berjalan lambat menghadapi krisis iklim yang sebenarnya lebih destruktif.
Keadilan Iklim dan Ketimpangan Global
Krisis iklim juga membuka luka lama dalam hubungan internasional terkait ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Negara-negara maju adalah penyumbang terbesar emisi karbon sejak Revolusi Industri, tapi justru negara berkembanglah yang paling merasakan dampaknya.
Negara kepulauan di Pasifik seperti Tuvalu, Kiribati, dan Maladewa terancam tenggelam, padahal kontribusi emisi mereka tidak sampai 1%. Sementara itu, negara-negara kaya masih memperdebatkan soal dana kompensasi iklim yang dijanjikan sejak Paris Agreement 2015.
Laporan OECD tahun 2023 menunjukkan bahwa janji pendanaan sebesar 100 miliar dolar per tahun untuk membantu negara berkembang beradaptasi dengan perubahan iklim belum pernah terpenuhi sepenuhnya. Banyak negara masih bergantung pada bantuan pinjaman, bukan hibah, yang justru menambah beban utang.
Kondisi ini menciptakan ketidakadilan baru di tingkat global yang mana jika tidak segera diatasi, bisa memicu ketegangan diplomatik yang berujung pada disintegrasi kepercayaan antarnegara. Dunia sedang menghadapi dilema moral terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang diciptakan bersama?

Institusi Global yang Belum Siap
Meski isu perubahan iklim telah menjadi agenda tetap dalam forum global seperti COP (Conference of the Parties), respons dunia masih bersifat reaktif, bukan transformatif.
Dewan Keamanan PBB, lembaga yang seharusnya menjaga stabilitas dunia, bahkan masih berdebat apakah krisis iklim bisa dikategorikan sebagai ancaman keamanan internasional. Padahal, dampaknya telah melampaui batas tradisional antara “keamanan nasional” dan “keamanan manusia.”
Badan-badan internasional seperti UNHCR (untuk pengungsi) atau WFP (untuk pangan) bekerja di bawah tekanan besar, tetapi tanpa dukungan struktural yang cukup. Sementara itu, negara-negara besar lebih fokus pada kompetisi teknologi hijau dan perebutan pengaruh ekonomi di balik narasi “energi bersih.”
Dengan kata lain, dunia sedang berhadapan dengan ancaman global, tapi masih berpikir dengan cara yang sempit. A global problem trapped in national thinking.
Untuk mencegah terjadinya fenomena yang dapat diibaratkan sebagai “perang tanpa peluru” ini, pendekatan keamanan global harus bertransformasi secara mendasar. Dunia tidak bisa lagi menunggu krisis berikutnya untuk bergerak, paradigma keamanan yang lama yang hanya berfokus pada militer dan pertahanan teritorial tidak cukup menghadapi ancaman yang sifatnya lintas batas dan tidak kasat mata seperti perubahan iklim.
Pertama, konsep climate security perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan nasional setiap negara. Ancaman iklim harus dipandang setara dengan ancaman keamanan tradisional, karena dampaknya langsung terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.
Adaptasi iklim bukan hanya tugas kementerian lingkungan hidup, tetapi juga bagian dari perencanaan strategis nasional. Negara yang tidak siap beradaptasi dengan krisis iklim pada akhirnya akan menghadapi risiko konflik internal dan kerentanan geopolitik.
Kedua, kerja sama internasional harus berbasis keadilan dan tanggung jawab bersama. Negara-negara maju yang historisnya menjadi penyumbang terbesar emisi karbon harus memimpin dalam pembiayaan adaptasi dan mitigasi bagi negara berkembang.
Bantuan tidak boleh berhenti di janji konferensi atau laporan tahunan, melainkan diwujudkan dalam transfer teknologi hijau, pendanaan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal. Keadilan iklim (climate justice) berarti memastikan bahwa mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini tidak menjadi pihak yang paling menderita karenanya.
Baca juga: Indonesia Perparah Krisis Iklim Akibat Food Estate Merauke
Ketiga, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda memiliki peran vital dalam menjaga momentum perubahan. Tekanan publik, riset independen, dan gerakan akar rumput menjadi kekuatan moral yang mendorong pemerintah untuk bertindak. Isu iklim bukan sekadar wacana diplomatik, tetapi perjuangan kemanusiaan yang menuntut keberanian kolektif untuk melawan ketidakpedulian.
Krisis iklim tidak bisa diselesaikan hanya dengan diplomasi elite di ruang tertutup. Ia memerlukan solidaritas lintas batas, lintas generasi, dan lintas kepentingan. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas politik global, melainkan keberlanjutan hidup manusia itu sendiri.
Jika dunia gagal memahami ini, maka perang terbesar abad ke-21 mungkin terjadi tanpa satu pun peluru ditembakkan, melainkan melalui kehancuran perlahan akibat kelalaian kita sendiri.
Dunia kini berjalan di ambang “perang baru”, perang yang tidak diumumkan, tidak memiliki musuh yang jelas, tapi korbannya nyata. Perubahan iklim perlahan mengikis sumber daya yang menopang kehidupan seperti air, udara, dan tanah.
Kita bisa saja menunda pembicaraan tentang solusi, tapi bumi tidak menunggu. Ia terus memanas, dan bersama dengannya, ketegangan sosial, politik, dan ekonomi kian mengeras. Setiap derajat suhu yang naik bukan hanya angka dalam laporan ilmiah, tetapi tanda bahaya bagi peradaban manusia.
Dunia diperkirakan telah menghabiskan triliunan dolar untuk membiayai perang dan persenjataan, namun masih berdebat tentang siapa yang harus menanggung biaya menyelamatkan bumi. Ironisnya, kita begitu siap menghadapi ancaman buatan manusia, tapi begitu lambat menanggapi ancaman yang diciptakan oleh kelalaian kita sendiri.
Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, ia bisa diibaratkan seperti perang tanpa peluru yang sudah berlangsung. Di dalamnya, tidak ada sekat antara pihak yang menang dan kalah. Semua terhubung dalam sistem yang sama rapuhnya.
Kita semua adalah bagian dari medan tempur ini, sebagian berjuang mencari solusi, sebagian masih menyangkal kenyataan, dan sebagian lainnya sudah menjadi korban diam dari kegagalan kolektif dunia.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah dunia siap menghadapi krisis iklim, tetapi berapa lama lagi kita bisa bertahan jika terus menunda perubahan? Setiap pilihan kecil yang diabaikan, setiap keputusan besar yang ditunda, mempercepat langkah kita menuju masa depan yang tak lagi bisa diselamatkan.
Dan ketika itu terjadi, sejarah tak akan menulis siapa yang paling bersalah, tetapi siapa yang paling diam.
Redaksi menerima artikel opini dengan panjang cerita minimal 700 kata, dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail redaksibenua@gmail.com disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat.
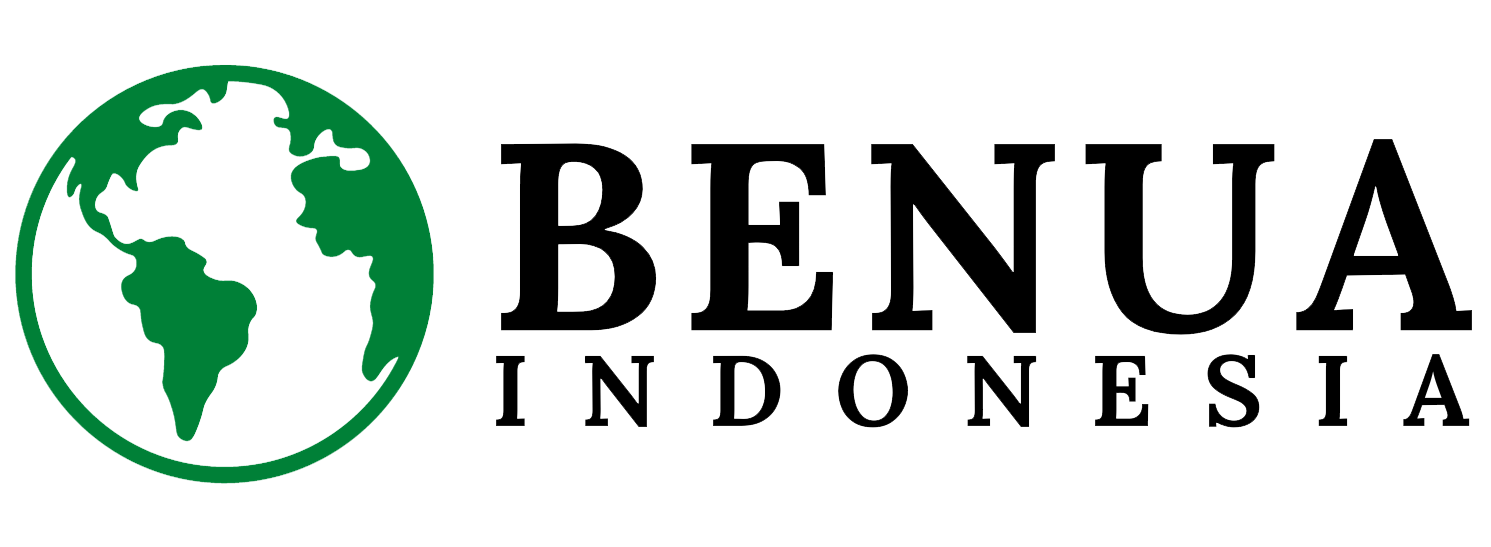













Leave a Reply
View Comments