- Agroforestri pampa di Desa Moa menunjukkan bahwa pelestarian hutan bisa tumbuh dari akar budaya, bukan hanya dari kebijakan negara.
- Melalui kearifan perempuan adat, sistem ini memadukan pertanian dan kehutanan untuk menjaga keseimbangan ekologi sekaligus memastikan ketahanan pangan keluarga.
- Pampa bukan sekadar lahan, tetapi ruang hidup yang menegaskan hubungan spiritual dan sosial antara manusia dan alam.
- Dari tangan perempuan adat Moa, lahir bukti bahwa tradisi bisa menjadi fondasi bagi masa depan bumi yang berkeadilan dan lestari.
Pagi di Desa Moa selalu dimulai dengan kesunyian yang hidup. Kabut tipis turun di antara lereng Kulawi Selatan, menyelubungi hamparan kebun yang membentang di kaki Pegunungan Gawalise.
Di sebuah rumah, Elisabet Heta, 52 tahun, tengah sibuk menyiapkan bekal. Di atas lantai, ia menata pisau, parang kecil, dan segenggam bibit cabai ke dalam baki—tas anyaman rotan dan bambu khas perempuan adat Moa. Setelah itu, tanpa banyak basa-basi, Elisabet bergegas keluar rumah.
“Saya mau ke pampa,” ujarnya pelan sambil tersenyum.
Bagi perempuan adat Moa, pampa bukan sekadar kebun. Ia adalah dapur kedua, ruang hidup, dan simbol kedaulatan pangan. Setiap pagi, hampir semua perempuan di desa ini berjalan ke pampa, lahan kecil di pinggiran hutan yang menjadi wilayah kelola perempuan. Di sanalah mereka menanam sayur, umbi, cabai, hingga bumbu dapur—semuanya hasil kerja tangan sendiri.
Setiap keluarga memiliki sekitar 300 meter persegi lahan pampa. Di sanalah tumbuh jagung yang diselingi kacang tanah, daun singkong, dan cabai yang memerah di antara rumpun serai. Tidak ada pupuk kimia, tidak ada pestisida. Semua bibit ditukar antarperempuan, hasil dari sistem barter yang diwariskan turun-temurun.
“Kalau saya punya bibit tomat, teman saya punya cabai. Kami saling tukar saja,” kata Elisabet.
Pampa menjadi sumber pangan utama keluarga. Sementara kaum laki-laki sibuk di ladang yang menghasilkan komoditas pasar seperti kopi atau kakao, kaum perempuan memastikan dapur tidak pernah kosong. Dengan begitu, rumah tangga masyarakat adat Moa tak perlu membeli bahan pangan dari luar.
Namun, bagi Elisabet, pampa bukan sekadar urusan dapur. Ia adalah warisan spiritual dari para leluhur, sebuah sistem yang menyatukan alam, manusia, dan Sang Pencipta.

Warisan Leluhur
Bagi Masyarakat Adat Topo Uma, salah satu subetnis Kulawi yang berbahasa Uma, pampa adalah warisan yang tak terpisahkan dari kehidupan. Mereka mengenal hutan melalui 15 tingkatan atau zonasi, masing-masing dengan fungsi dan aturan berbeda. Di antara semua itu, pampa adalah satu-satunya zona yang secara eksklusif menjadi milik perempuan.
Agustim Mpadjama, atau yang disebut tina ngata (ibu kampung), menjelaskan bahwa pampa bukan sekadar lahan, tetapi bagian dari sistem pengetahuan ekologis masyarakat Moa. Dalam filosofi adat Kulawi dikenal tiga pilar kehidupan: hintuwu (hubungan antar manusia), katuwuan (hubungan manusia dengan alam), dan petukua (hubungan dengan Sang Pencipta). Pampa adalah jantung dari katuwuan itu.
“Dulu, sebelum membuka lahan pampa, kami harus menggelar upacara adat. Meminta restu pada Tope Hoi, penguasa alam semesta,” ujar Agustim.
Upacara itu dipimpin oleh Tetua Adat, yang dipercaya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh alam. Mereka memohon kesuburan tanah, perlindungan dari hama, dan keselamatan bagi para perempuan yang akan bekerja di pampa. Namun, sejak masuknya agama Kristen dan kuatnya pengaruh gereja, ritual adat itu perlahan digantikan oleh ibadah syukur atau wunca di gereja.
Meskipun begitu, nilai-nilai spiritual itu tidak hilang. Ia menempel pada cara perempuan bekerja—penuh kehati-hatian, rasa hormat, dan solidaritas.
Baca juga: Merawat Pampa, Hutan Perempuan Adat Moa
Setiap pagi, perempuan Moa bekerja di pampa dalam kelompok yang disebut Mome Ala Pale—sebuah sistem kerja gotong royong yang telah ada jauh sebelum negara mengenal istilah “koperasi”. Di bawah sinar matahari, 20 hingga 23 perempuan bekerja bergantian di lahan anggota kelompok.
“Kalau hari ini saya bantu di pampa Elisabet, besok dia gantian bantu saya. Tidak ada uang, yang penting tenaga dan kebersamaan,” kata Agustim.
Sistem ini tidak sekadar mengatur pekerjaan. Ia juga menjadi ruang sosial perempuan adat—tempat berbagi cerita, bertukar pengetahuan, hingga menyelesaikan persoalan keluarga. Di pampa, tidak ada hierarki. Semua duduk sejajar, tertawa, dan makan bersama hasil panen mereka.
Namun, aturan adat tetap dijaga ketat. Ada pantangan yang disebut palia. Misalnya, jika hujan turun saat pembukaan lahan di pagi hari, pekerjaan harus dihentikan. Itu pertanda buruk. Demikian pula jika terdengar suara gemuruh angin—mereka harus berhenti sejenak, menunggu sepuluh menit hingga alam kembali tenang.
“Kalau dilanggar, bisa kena musibah. Itu sudah sering terjadi,” kata Agustim dengan nada yakin.
Bagi perempuan adat Moa, pantangan bukan bentuk takhayul, melainkan mekanisme ekologis—cara leluhur mengajarkan kehati-hatian dan penghormatan pada alam.

Ketimpangan dari dalam Hutan
Namun, pampa tak lagi seluas dulu. Sebagian lahan yang dulu penuh sayur dan umbi kini berubah menjadi hutan yang ditumbuhi kopi dan kakao. Sebagian lagi bahkan tak bisa diakses karena masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
Perubahan itu terjadi perlahan. Awalnya, pada masa kolonial Belanda, kopi menjadi tanaman primadona. Setelah kemerdekaan, kakao menyusul. Harga yang tinggi membuat masyarakat mulai menanam kedua komoditas itu di berbagai zona, termasuk pampa.
“Dulu, Moa itu terkenal. Tahun 1950-an, kopi dari sini jadi andalan Sulawesi Tengah. Tahun 1990-an, giliran kakao,” kenang Helni Gopi, tokoh perempuan adat yang kini memimpin kelompok tani pampa.
Namun, kejayaan itu berubah menjadi tekanan ketika negara menetapkan kawasan konservasi Lore Lindu pada 1993. Tanpa dialog, 85 persen wilayah adat Moa masuk ke dalam kawasan taman nasional. Sejak itu, akses masyarakat terhadap hutan dibatasi.
“Pohon kopi dan kakao yang ditanam orang tua kami ditebang petugas. Katanya karena itu masuk kawasan hutan negara,” kata Helni pelan.
Warga yang mencoba bertahan dituduh sebagai perambah hutan. Padahal, mereka hanya mempertahankan kebun yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, ruang hidup semakin sempit, dan perempuan kehilangan sebagian wilayah pampa-nya.
Namun, alih-alih menyerah, mereka mencari jalan baru untuk bertahan—dengan cara yang lebih berkelanjutan.
Baca juga: Ekofeminisme; Suara Perempuan dan Jeritan Alam
Keterbatasan lahan membuat perempuan Moa mulai memadukan sistem pertanian mereka dengan pepohonan—sebuah praktik yang kini dikenal dengan nama agroforestri.
“Leluhur kami sebenarnya sudah melakukan itu sejak dulu,” kata Helni. “Kami hanya menyebutnya dengan cara lama: menanam sambil menjaga.”
Di pampa, kini tumbuh tumpangsari antara sayur, jagung, kopi, kakao, bahkan pohon aren. Akar-akar pepohonan itu menjaga air dan tanah dari erosi, sementara tanaman pangan di bawahnya memastikan dapur tetap terisi.
Di sela-sela kebun, mereka menanam tanaman obat seperti kunyit, jahe, dan kencur. Semua dikelola tanpa pupuk kimia. Sisa panen yang tidak dikonsumsi dijual di pasar Kulawi. Pendapatan itu digunakan untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari.
“Kalau dulu pampa hanya untuk makan, sekarang bisa juga jadi sumber tambahan pendapatan. Tapi tetap kami jaga agar tidak merusak tanah,” kata Elisabet sambil memungut daun singkong.
Para perempuan juga mengembangkan sistem pembibitan lokal. Mereka mengoleksi biji kopi tua, memilih yang terbaik, dan menanam kembali di lahan pampa. Tak ada satu pun bibit yang dibeli dari luar. Semua berasal dari hasil panen sebelumnya.
Agroforestri ala Moa bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan bentuk adaptasi ekologis dan kemandirian perempuan adat. Mereka belajar dari keterbatasan, lalu menciptakan solusi dengan nilai-nilai sendiri.

Berjuang Lewat Pengakuan Hutan Adat
Namun, keberlanjutan pampa tetap bergantung pada satu hal: pengakuan atas tanah dan hutan adat.
Pada 2017, masyarakat adat Moa mengajukan usulan pengakuan hutan adat seluas 7.738 hektar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prosesnya panjang dan melelahkan. Mereka didampingi oleh Karsa Institute dan Kemitraan Partnership, dua lembaga yang membantu memperkuat data wilayah adat.
Empat tahun berlalu, pada 10 September 2021, pengakuan itu akhirnya datang—namun hanya 1.484 hektar yang diakui negara. “Jauh sekali dari yang kami usulkan. Tapi kami tetap bersyukur, itu langkah pertama,” kata Helni.
Bagi perempuan adat Moa, pengakuan itu bukan sekadar soal luas wilayah, tapi soal keadilan ekologis. Mereka ingin diakui sebagai penjaga hutan, bukan dianggap perusak. Dalam sistem adat Topo Uma, hutan tidak pernah dimiliki perorangan, melainkan dijaga bersama.
“Kalau hutan rusak, kami juga yang kehilangan. Bukan hanya tanah, tapi kehidupan,” ujarnya.
Saat ini, mereka tengah memperkuat tata kelola pampa berbasis hukum adat. Pemerintah desa turut dilibatkan untuk membuat peraturan lokal yang melindungi wilayah perempuan. Anak-anak muda dilatih untuk mengenali kembali batas adat dan menulis cerita tentang pampa mereka sendiri.
Bagi masyarakat adat Moa, hutan bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan bagian dari identitas kultural. Hutan adalah “urat nadi” kehidupan mereka—sumber pangan, obat, bahan bangunan, bahkan spiritualitas.
“Sejak dulu, kami tidak bisa lepas dari hutan,” kata Helni Gopi, tokoh perempuan adat Moa. “Hutan memberi kami makan, dan kami menjaga agar ia tetap hidup.”
Hubungan itu tampak nyata dalam keseharian. Setiap aktivitas di hutan—menebang, menanam, atau mengambil hasil bumi—harus mengikuti aturan adat yang ketat. Tidak boleh menebang pohon yang tumbuh di sumber mata air. Tidak boleh membuka lahan di lereng curam. Semua diatur dalam hukum adat Topo Uma yang diwariskan turun-temurun.
Dalam konteks itu, perempuan adat Moa menjadi garda depan penjaga hutan. Mereka yang pertama kali mengetahui jika ada perubahan tutupan lahan atau aktivitas mencurigakan di sekitar kawasan. Mereka pula yang menjadi suara paling keras menolak perusakan hutan.
Hal itu diakui oleh Desmon Mantaili, Program Manager Karsa Institute, lembaga yang lebih dari satu dekade mendampingi masyarakat Moa dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Perempuan adat Moa memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat dalam pelestarian lingkungan,” kata Desmon. “Dalam banyak kasus, mereka justru lebih tegas dibanding petugas taman nasional dalam melarang penebangan liar.”
Baca juga: Perempuan dan Masa Depan Terhadap Lingkungan
Selama pendampingan di Moa, Desmon menyaksikan sendiri bagaimana agroforestri pampa menjadi sistem hidup yang menyatu dengan perempuan adat. Ia tidak sekadar ladang, melainkan ruang belajar dan transmisi pengetahuan.
“Di sana, setiap tanaman punya cerita. Pohon kopi dari nenek mereka, jahe dari tetangga desa, dan pohon aren yang ditanam bersama suami ketika baru menikah,” ujarnya.
Pampa menjadi ruang interaksi antara manusia dan alam, juga antara generasi tua dan muda. Anak-anak belajar mengenali tumbuhan, menghitung musim, dan memahami makna kerja kolektif melalui sistem Mome Ala Pale. Dari pampa, mereka belajar bahwa ketahanan pangan dan pelestarian hutan tidak bisa dipisahkan.
Menurut Desmon, nilai penting dari sistem ini adalah keberlanjutan. Dalam satu petak pampa, perempuan adat bisa menanam sayur untuk kebutuhan harian, tanaman keras untuk jangka panjang, serta tanaman penghasil uang seperti kopi dan kakao. Dengan begitu, mereka memiliki diversifikasi ekonomi alami tanpa harus merusak hutan baru.
“Agroforestri pampa adalah contoh ideal pembangunan rendah emisi berbasis komunitas,” ujarnya.
Setiap sore, ketika matahari mulai condong ke barat, perempuan-perempuan Moa kembali dari pampa. Mereka membawa hasil panen di dalam baki: kacang tanah, cabai, sayur daun singkong, dan biji kopi yang dijemur di halaman rumah. Anak-anak menyambut di depan tangga, membantu menurunkan hasil kebun.
Bagi generasi muda Moa, pampa bukan lagi sekadar kebun orang tua mereka, melainkan ruang belajar. Di sanalah mereka diajarkan membaca arah angin, mengenali musim, dan memahami tanda-tanda alam.
“Anak-anak harus tahu dari mana makanan berasal. Kalau tidak, mereka bisa lupa pada tanah,” kata Elisabet sambil menatap kebun di kejauhan.
Perempuan Moa berencana ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah dan beberapa lembaga pendamping untuk mengembangkan ekowisata edukatif di pampa. Tujuannya bukan komersial, tetapi memperlihatkan bahwa cara hidup adat bisa berjalan seiring dengan pelestarian hutan.
Mereka juga sedang merencanakan untuk mengembangkan produk lokal berbasis pampa—seperti bubuk jahe, kopi organik, dan keripik singkong. Hasil penjualan nantinya akan digunakan untuk mendukung pendidikan anak-anak di desa.
“Dulu kami dianggap tertinggal karena bertani tradisional. Sekarang kami tahu, yang kami lakukan justru menjaga bumi tetap hidup,” kata Helni sambil tertawa kecil.

Ekologi yang Berakar pada Budaya
Wilayah kelola Pampa kini menjadi perhatian akademisi, aktivis lingkungan, dan pembuat kebijakan. Bagi banyak pihak, ia menjadi model teknologi ekologi yang berakar pada budaya lokal. Tak hanya efektif menjaga hutan, tapi juga memiliki penerimaan sosial yang kuat—sesuatu yang sering absen dalam program konservasi modern.
Sistem pengelolaan pampa itu dikenal dengan sebutan agroforestri pampa, istilah yang dipopulerkan oleh Prof. Syukur Umar, pakar ekonomi sumber daya hutan dari Universitas Tadulako.
Dalam bukunya Agroforest Pampa (2022), ia menulis bagaimana praktik tradisional perempuan Moa membentuk forest garden, kebun yang menyerupai hutan alami namun berfungsi ganda: menjaga lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
“Agroforestri pampa yang dikelola perempuan adat Moa menjadi jaring pengaman setiap rumah tangga,” ujar Syukur Umar. “Apalagi mereka hidup di tepi kawasan Taman Nasional Lore Lindu.”
Dari penelitian lapangannya, Syukur menemukan bahwa pampa memperlihatkan struktur ekologis yang kompleks: pohon, perdu, tanaman semusim, bahkan rumput—semuanya membentuk lapisan vegetasi seperti hutan alam.
Dalam satu petak pampa, bisa ditemukan hingga belasan jenis tanaman dengan fungsi berbeda: tanaman kayu, buah, sayur, hingga obat-obatan. Pola ini menciptakan keseimbangan alami yang mampu memperbaiki kesuburan tanah dan menjaga siklus air.
“Ini teknik tradisional yang tumbuh dari kebudayaan, bukan hasil intervensi teknokrat,” tulisnya.
Desa Moa memang berada di ujung paling selatan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah—desa terakhir sebelum memasuki belantara Lore Lindu. Dari ibu kota kecamatan, Gimpu, desa ini hanya bisa dicapai dengan sepeda motor selama tiga jam menyusuri jalan sempit di tepi jurang dan sungai Lariang.
Keterisolasian geografis itu membuat masyarakat Moa hidup dalam kedekatan yang sangat kuat dengan alam. Sebagian besar wilayahnya dilingkari hutan lindung dan kawasan Taman Nasional Lore Lindu, yang luasnya mencapai 215 ribu hektar. Kawasan itu menjadi rumah bagi beragam spesies endemik Sulawesi—anoa, maleo, dan kuskus beruang.
Baca juga: Perempuan Adat Sumba Menulis Lewat Tenunan
Di tengah bentang hutan itu, agroforestri pampa tumbuh sebagai oase kecil yang penuh kehidupan. Sistem ini menjadi penyangga alami kawasan taman nasional, karena mencegah pembukaan hutan baru dan menekan perambahan.
“Agroforest pampa adalah solusi terbaik bagi masyarakat di sekitar taman nasional,” kata Syukur Umar. “Ia memadukan pertanian dan kehutanan, menghasilkan pangan tanpa merusak ekosistem.”
Lebih dari itu, sistem ini lahir dari pengalaman hidup, bukan dari proyek pembangunan. Tidak ada pelatihan modern, tidak ada bantuan teknologi. Perempuan Moa menanam berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara lisan: kapan musim hujan tiba, bagaimana mengenali kesuburan tanah dari warna daun, dan jenis pohon apa yang bisa menjadi pelindung tanaman di bawahnya.
“Ini bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa lahir dari kearifan lokal,” ujar Syukur.
Syukur Umar menyebutnya sebagai “inovasi tanpa laboratorium.” Nilai ekologisnya jelas: memperkaya biodiversitas, menjaga cadangan karbon, menahan erosi. Tapi yang lebih penting, sistem ini memulihkan relasi antara manusia dan hutan yang sempat terputus akibat kebijakan negara.
Dalam konteks Desa Moa—yang sebagian besar wilayahnya berada di zona penyangga Taman Nasional Lore Lindu—pampa menjadi benteng terakhir keberlanjutan. Ia mencegah konflik lahan, sekaligus menghidupkan kembali filosofi adat hintuwu, katuwuan, dan petukua.
“Melalui pampa, perempuan adat Moa tidak hanya memberi makan keluarganya, tapi juga memberi kehidupan bagi hutan,” tulis Syukur dalam bukunya.
Kini, nama Moa mulai dikenal di forum-forum lingkungan. Beberapa organisasi lokal dan internasional menjadikan agroforestri pampa sebagai studi kasus pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Pemerintah daerah Sigi juga mulai melihat potensi ini sebagai model replikasi untuk desa-desa lain di sekitar Lore Lindu.
Namun, bagi perempuan adat Moa, mereka tidak sedang mencari pengakuan. Mereka hanya melakukan apa yang telah diajarkan leluhur: menjaga keseimbangan antara tanah, manusia, dan Sang Pencipta.
“Kami tidak menanam untuk pasar, tapi untuk hidup,” kata Elisabet Heta suatu pagi di pampa miliknya. “Kalau hutan rusak, kami pun rusak.”
Setiap sore, Elisabet dan puluhan perempuan lain kembali dari kebun, membawa hasil panen di dalam baki rotan. Di sepanjang jalan, mereka berbagi tawa dan cerita, seolah lelah tak pernah menjadi beban. Di balik kesederhanaan itu, mereka telah menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertani: mereka merawat bumi dengan cara yang paling manusiawi.

Harapan yang Tumbuh dari Tanah
Kisah perempuan adat Moa memperlihatkan wajah lain dari konservasi—bahwa pelestarian alam tak selalu lahir dari undang-undang atau program pemerintah, melainkan dari kesadaran kultural yang tumbuh di akar masyarakat.
Di lembah Kulawi, sistem agroforestri pampa menjadi bukti nyata bahwa perempuan bukan sekadar penerima dampak, tetapi pencipta solusi. Melalui tangan mereka, hutan bukan hanya dijaga, tapi dihidupkan kembali. Pampa menegaskan bahwa menjaga hutan tidak berarti menolak kemajuan, melainkan menapaki jalan pembangunan yang lebih adil dan lestari.
“Kalau semua masyarakat di tepi hutan menerapkan sistem seperti ini,” ujar Desmon Mantaili, “mungkin kita tidak perlu lagi bicara tentang konflik antara konservasi dan kehidupan.”
Dari dapur-dapur sederhana, filosofi hidup itu berakar. Perempuan Moa menanam bukan untuk pasar, tetapi untuk hidup bersama alam. Mereka menolak logika eksploitatif yang memisahkan manusia dari hutan. Saat negara melihat hutan sebagai batas administratif, mereka memaknainya sebagai ibu yang memberi kehidupan.
Baca juga: Hidup dari Alam, Perempuan Adat Tolak Tambang Masuk Banggai Kepulauan
Kini, di tengah krisis iklim global dan deforestasi yang kian meluas, praktik pampa menjadi cermin: bahwa masyarakat adat—terutama perempuan—bisa menjadi ujung tombak solusi. Di Moa, hutan bukan lagi sekadar lanskap hijau di peta, melainkan rumah bersama yang memelihara keberlanjutan.
Pampa bukan sekadar lahan pertanian, melainkan simbol harapan. Ia menunjukkan bahwa tradisi tak bertentangan dengan kemajuan, melainkan menawarkan paradigma baru: pembangunan yang berakar pada kearifan lokal, berkeadilan gender, dan berkelanjutan ekologis.
“Selama kami masih punya pampa,” kata Elisabet, “kami tidak akan kelaparan. Hutan memberi makan kami, dan kami berkewajiban menjaganya.”
Senja turun di atas Kulawi. Kabut tipis kembali menyelimuti lembah Moa, sementara asap dapur mengepul di antara rumah-rumah bambu. Dari jendela kecil rumah Elisabet, aroma kopi yang baru disangrai bercampur dengan tawa anak-anak.
Di luar, pampa menunggu hari esok—sebuah taman kehidupan yang tumbuh dari tangan-tangan perempuan. Di sanalah harapan berakar: sederhana, hijau, dan penuh cinta.
Tulisan ini adalah bagian dari kolababorasi Jaga Wallacea, sindikasi 12 media alternatif di kawasan Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara. Tulisan ini bagian dari serial #JurnalisJagaWallacea
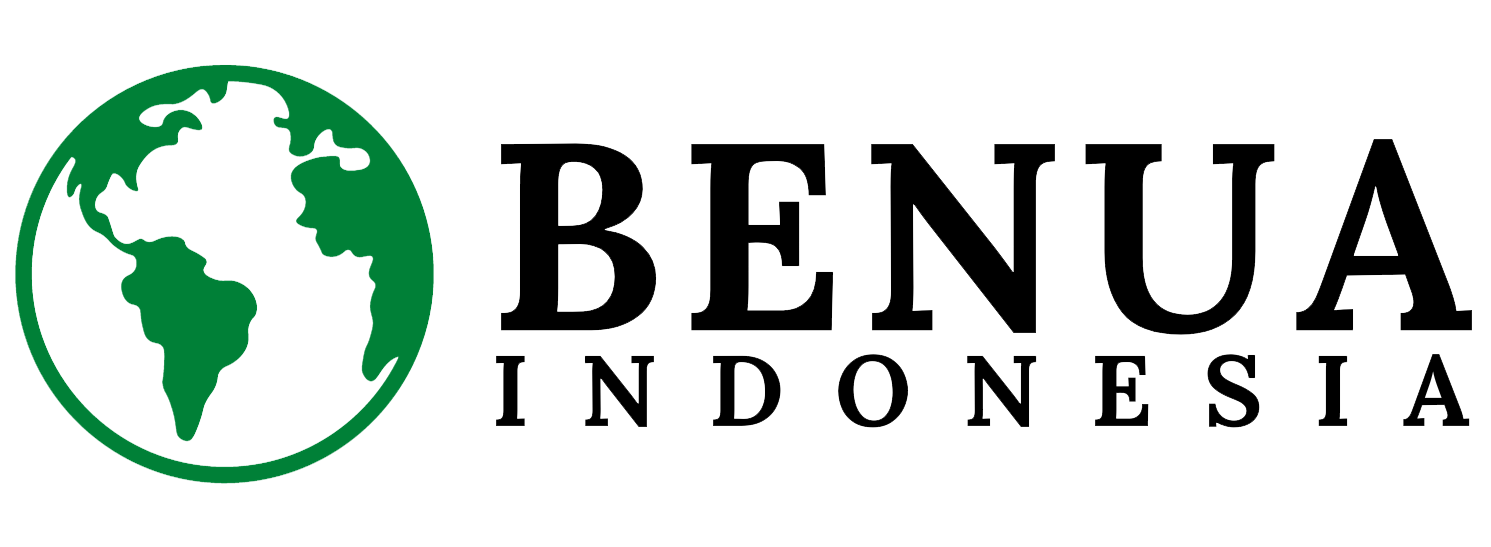











Leave a Reply
View Comments