- Revisi Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR 2025. Berbagai organisasi masyarakat sipil mengingatkan, seharusnya, revisi UU Kehutanan ini jadi momentum penting mengoreksi ketimpangan tata kelola hutan dan memperkuat komitmen negara terhadap keadilan sosial dan ekologis.
- Dalam revisi ini, jangan sampai jadi proses terburu-buru, tertutup dan minim partisipasi publik. Alih-alih memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat serta komunitas lokal, mereka khawatir, revisi ini malah membuka ruang lebih luas bagi ekspansi industri ekstraktif dalam kawasan hutan melalui pelonggaran jalur legal-formal.
- Muhammad Ichwan, Direktur Eksekutif Nasional (DEN) JPIK mengatakan, lebih mengkhawatirkan, revisi tanpa kajian evaluatif yang menyeluruh terhadap implementasi UU Kehutanan, selama lebih dari dua dekade. Ketiadaan evaluasi ini memperlihatkan dorongan perubahan lebih bermuatan politis dan ekonomis daripada berdasarkan kebutuhan objektif untuk memperbaiki tata kelola kehutanan secara struktural dan berkeadilan.
- Sarah Agustio, Peneliti Nugal Ecologica Indonesia juga mengatakan, revisi UU Kehutanan memuat sejumlah isu mendasar dan risiko krusial. Apabila, tak ada antisipasi seksama dalam proses legislasi akan merusak tata kelola hutan yang demokratis, adil, dan berkelanjutan.
Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2025. Pemerintah menyatakan bahwa revisi ini diperlukan untuk menyelaraskan tata kelola kehutanan nasional dengan perkembangan regulasi dan kebijakan pembangunan, termasuk harmonisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja serta penguatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, proses revisi yang dijalankan secara terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil. Alih-alih memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat serta komunitas lokal, revisi ini dinilai justru dikhawatirkan membuka ruang yang lebih luas bagi ekspansi industri ekstraktif ke dalam kawasan hutan melalui jalur legal-formal yang diperlonggar.
Muhammad Ichwan, Direktur Eksekutif Nasional (DEN) Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mengatakan, yang ebih mengkhawatirkan, revisi ini dilakukan tanpa disertai kajian evaluatif yang menyeluruh terhadap implementasi UU Kehutanan selama lebih dari dua dekade.
“Ketiadaan evaluasi ini memperlihatkan bahwa dorongan perubahan lebih bermuatan politis dan ekonomis daripada berdasarkan kebutuhan objektif untuk memperbaiki tata kelola kehutanan secara struktural dan berkeadilan,” kata Muhammad Ichwan dalam rilis yang diterima Mongabay.
Ichwan bilang, konteks kebijakan ini hadir dalam situasi di mana tekanan terhadap kawasan hutan terus meningkat. Sektor kehutanan kini berada dalam pusaran ekspansi investasi berbasis lahan, termasuk perkebunan sawit, pertambangan, proyek ketahanan pangan dan energi, yang dilegitimasi oleh kerangka deregulasi dalam UU Cipta Kerja.
Menurut data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 175.400 hektare, meningkat dari 121.100 hektare pada tahun sebelumnya. Sekitar 69,3% deforestasi terjadi di dalam kawasan hutan.
Di sisi lain, analisis Auriga Nusantara menyebut angka deforestasi mencapai 261.575 hektare, dengan sebagian besar kehilangan hutan terjadi di area konsesi industri besar. Perbedaan angka ini menandakan lemahnya akuntabilitas dalam sistem pemantauan dan pelaporan deforestasi Indonesia.
Menurut Ichwan, arah revisi UU Kehutanan yang menekankan skema multiusaha kehutanan (MUK), perdagangan karbon, serta fleksibilitas izin pemanfaatan kawasan hutan tanpa memperjelas perlindungan sosial-ekologis, dinilai bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia dalam Perjanjian Paris dan Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Baca juga: UU Kehutanan Dinilai Gagal Memerdekakan Rakyat
Dalam dokumen ENDC yang disampaikan Indonesia kepada UNFCCC pada Juli 2022, kata dia, pemerintah menyatakan target penurunan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional, dengan sektor kehutanan melalui strategi FOLU Net Sink 2030 sebagai sektor utama penurunan emisi.
Namun, kata Ichwan, revisi UU Kehutanan ini justru mengandung risiko tinggi terhadap pencapaian target FOLU Net Sink, karena membuka kembali ruang legalisasi deforestasi dan ekspansi usaha atas nama restorasi atau mitigasi iklim tanpa perlindungan yang memadai terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi dan wilayah kelola rakyat. Ini berpotensi menjadi langkah regresif dalam aksi iklim nasional.
Di sisi lain, kata dia, hak konstitusional masyarakat adat atas wilayah kelola mereka masih belum terjamin secara eksplisit dalam substansi revisi. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan harus diakui sebagai wilayah kelola masyarakat hukum adat.
“Tetapi dalam praktik, pengakuan atas hutan adat masih bergantung pada sistem administrasi yang diskriminatif dan berlarut-larut,” jelaasnya.
Lebih jauh, kata dia, belum adanya pengakuan eksplisit atas prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam proses legislasi maupun perizinan kehutanan, menunjukkan regresi terhadap standar hak asasi manusia internasional sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang telah diratifikasi secara prinsip oleh Indonesia.
Rencana pemerintah membuka hingga 20 juta hektare kawasan hutan untuk proyek pangan, energi, dan infrastruktur sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045, jika tidak disertai mekanisme perlindungan sosial-ekologis yang kuat, akan memperburuk deforestasi dan konflik tenurial.
Padahal ketentuan minimal 30% kawasan hutan per DAS dan/atau pulau, yang telah dihapus dalam UU Cipta Kerja, merupakan standar ilmiah minimum (FAO) untuk menjaga fungsi ekologis hutan dalam menopang kehidupan manusia, air, dan keanekaragaman hayati.
Dalam kerangka tersebut, masyarakat sipil memandang bahwa proses dan substansi revisi UU Kehutanan harus ditinjau ulang secara mendasar. Revisi ini tidak boleh menjadi sarana legalisasi pengambilalihan kawasan hutan oleh elite ekonomi-politik, tetapi sebaliknya harus menegaskan keberpihakan negara pada prinsip keadilan ekologis, penghormatan hak konstitusional masyarakat adat dan lokal, serta komitmen terhadap aksi iklim global.
“Oleh karena itu, masyarakat sipil memandang perlu untuk menyuarakan posisi yang tegas terhadap proses dan substansi revisi UU Kehutanan, agar tidak menjadi alat legalisasi pengambilalihan kawasan hutan oleh kepentingan industri semata, tetapi justru menguatkan prinsip keadilan ekologis, keberlanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Akan Merusak Tata Kelola
Sarah Agustio, Peneliti Nugal Ecologica Indonesia juga mengungkapkan, revisi UU Kehutanan memuat sejumlah isu mendasar dan risiko krusial yang, apabila tidak diantisipasi secara seksama dalam proses legislasi, akan merusak tatanan tata kelola hutan yang demokratis, adil, dan berkelanjutan.
Isu pertama yang harus secara serius diperhatikan dan diakomodasi dalam perumusan kebijakan yakni: Reduksi Makna Hutan sebagai Ruang Hidup. Sarah bilang, revisi UU Kehutanan masih berpijak pada paradigma teknokratis yang melihat hutan semata sebagai objek biofisik untuk dieksploitasi ekonomi.
“Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa hutan adalah ruang hidup yang melekat dalam identitas dan sistem penghidupan masyarakat adat dan lokal. Undang-undang kehutanan yang baru harus mengafirmasi dimensi sosial, budaya, dan spiritual hutan serta menjamin perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut,” Sarah Agustio dalam rilis yang diterima Mongabay.
Isu kedua yakni; Dominasi Korporasi atas Kawasan Hutan melalui Skema Usaha dan Karbon. Sarah menjelaskan revisi mendorong perluasan skema multiusaha kehutanan (MUK) dan pasar karbon tanpa landasan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis yang kuat.
Skema ini, kata Sarah, akan membuka peluang bagi korporasi besar untuk menguasai kawasan hutan dengan dalih mitigasi iklim dan restorasi ekosistem, namun justru berpotensi mengusir masyarakat adat dari wilayah kelolanya.
“Perumusan UU harus memastikan bahwa pendekatan ekonomi hijau tidak menjadi alat baru perampasan lahan,” ucapnya.
Isu ke tiga, yakni; absennya Jaminan Hukum atas Hak Masyarakat Adat dan Lokal. Pasalanya, pengakuan hak masyarakat adat masih dibatasi oleh proses administratif yang rumit dan diskriminatif. Padahal, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah mengakui eksistensi hutan adat sebagai bagian dari hak konstitusional.
“Revisi UU Kehutanan harus menjamin pengakuan langsung dan perlindungan hak-hak tersebut secara eksplisit, tidak bersyarat pada proses birokrasi,” jelasnya.
Isu ke empat, yakni: pengabaian Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemantauan Independen. Proses legislasi dan implementasi kebijakan kehutanan hingga saat ini minim mengakomodasi partisipasi bermakna (meaningful participation). Padahal, masyarakat sipil dan pemantau independen telah terbukti berkontribusi besar dalam pengawasan dan pengungkapan pelanggaran kehutanan.
Misalnya; pemantauan hutan dari JPIK telah menghasilkan pelaporan 171 kasus dugaan ketidak sesuaian (NC) dan pelanggaran kehutanan yang disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi SVLK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Penegak Hukum dan lembaga pemerintah. Hasilnya, hanya 75% kasus telah ditangani oleh pihak terkait.
Baca juga: UU Kehutanan Akan Direvisi, Bisa Disusupi Kepentingan Korporasi?
“Revisi UU harus menjamin ruang legal yang melindungi dan mengakui peran masyarakat sipil sebagai bagian dari sistem akuntabilitas tata kelola hutan,” katanya.
Isu ke lima, yakni; Sentralisasi Kewenangan yang Melemahkan Pemerintah Daerah. Sarah menjelaskan, revisi menunjukkan kecenderungan menarik kewenangan pengelolaan kehutanan ke pusat, yang berpotensi menafikan peran pemerintah daerah dan komunitas lokal.
“Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. UU Kehutanan harus memberikan ruang afirmatif bagi daerah dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan,” tegasnya.
Isu ke enam, yakni: Dekriminalisasi Terselubung terhadap Kejahatan Kehutanan. Sarah bilang, dengan adanya isu dekriminalisasi terselubung terhadap kejahatan kehutanan menimbulkan Indikasi pelemahan sanksi terhadap pelanggaran kehutanan dalam revisi sangat mengkhawatirkan.
Tindakan ilegal seperti pembalakan liar, konversi hutan tanpa izin, dan pelanggaran korporasi dapat diselesaikan secara administratif. Hal ini, kata Sarah, juga akan melemahkan efek jera dan mencederai upaya perlindungan hutan secara sistemik. Menurutnya, UU baru harus mempertegas sanksi pidana dan memperkuat mekanisme penegakan hukum.
Isu ke tujuh, yakni: Ketiadaan Jaminan atas Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Sarah, transparansi data perizinan, status kawasan, tutupan hutan, konflik tenurial, dan hasil pengawasan merupakan prasyarat dasar untuk pengawasan publik.
“Revisi yang tidak menyebut secara eksplisit keterbukaan informasi menandakan kemunduran dalam prinsip tata kelola yang akuntabel dan inklusif,” katanya.
Isu ke delapan, yakni: Rencana Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan Tanpa Perlindungan Sosial-Ekologis. Ia bilang, rencana besar dalam RPJPN 2025–2045 untuk membuka kawasan hutan bagi proyek pangan dan energi sangat berisiko mempercepat deforestasi, krisis air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menambah tekanan pada wilayah kelola rakyat.
“UU Kehutanan harus memuat ketentuan yang ketat dan berbasis prinsip kehati-hatian serta FPIC sebelum implementasi proyek-proyek tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, delapan isu krusial ini tidak diakomodasi secara serius dalam revisi UU Kehutanan, maka kebijakan yang dihasilkan akan bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis, hak asasi manusia, serta komitmen iklim yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris dan NDC Indonesia.
“Karena itu, proses legislasi harus melibatkan secara aktif dan bermakna seluruh pemangku kepentingan, terutama mereka yang selama ini berada di garda depan perlindungan hutan: masyarakat adat, komunitas lokal, dan pemantau independen,” ucapnya.

Mengoreksi Ketimpangan Tata Kelola Hutan
Di tengah meningkatnya ancaman terhadap kelestarian hutan Indonesia—dari perluasan industri ekstraktif, konversi lahan, hingga konflik tenurial yang berkepanjangan—revisi Undang-Undang Kehutanan menjadi salah satu titik krusial dalam menentukan masa depan hutan kita.
Menurut JPIK, revisi UU Kehutanan bisa momentum penting untuk mengoreksi ketimpangan tata kelola hutan dan memperkuat komitmen negara terhadap keadilan sosial dan ekologis. Jika dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, meaningful participation, dan berbasis hak, maka revisi ini dapat menjadi landasan bagi pembaruan tata kelola hutan yang progresif dan berkelanjutan.
Muhammad Ichwan menyampaikan bahwa JPIK telah merumuskan delapan rekomendasi strategis yang perlu menjadi pijakan dalam proses revisi. Rekomendasi ini dirancang untuk memastikan bahwa kehutanan di Indonesia tidak lagi dipahami secara sempit sebagai urusan teknokratis, melainkan sebagai isu multidimensi yang menyangkut ruang hidup, identitas budaya, dan hak atas lingkungan yang sehat.
Pertama, revisi ini harus dimulai dengan rekonstruksi paradigma kehutanan yang menempatkan keadilan sosial dan ekologis sebagai dasar. Hutan bukan semata objek biofisik yang bisa dikelola dari balik meja, melainkan ruang hidup yang penuh nilai sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
“Karena itu, pendekatan transdisiplin—yang menggabungkan ekologi, hukum, antropologi, dan sosiologi—menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan,” kata Muhammad Ichwan.
Kedua, proses penyusunan undang-undang ini harus menjamin partisipasi bermakna dari semua pihak, khususnya masyarakat adat, perempuan, pemuda, kelompok rentan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Ia bilang, partisipasi yang dimaksud bukan sekadar formalitas, tetapi mencakup keterlibatan nyata dalam perumusan kebijakan, akses terhadap informasi, dan hak menyampaikan keberatan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Baca juga: Hutan Sosial, Klinik Hijau di Masela
Ketiga, hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal harus diakui secara eksplisit dan dilindungi secara nyata. Tidak boleh lagi hak mereka bergantung pada prosedur administratif yang diskriminatif dan berlarut-larut. Ia tegaskan, Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus menjadi standar dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adat dan kelola rakyat.
Keempat, negara perlu memberikan perlindungan hukum terhadap pemantau independen kehutanan. Peran masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan kebijakan kehutanan harus diakui dan dilindungi. Hal ini termasuk perlindungan bagi pelapor pelanggaran serta jaminan atas kebebasan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Kelima, sanksi terhadap pelaku kejahatan kehutanan—baik individu, korporasi, maupun pejabat negara—harus ditegakkan secara tegas dan konsisten. Revisi UU tidak boleh menjadi celah untuk melemahkan akuntabilitas hukum. Sebaliknya, harus memperkuat efek jera dan menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hutan dan keadilan ekologis.
Keenam, substansi revisi harus sepenuhnya sinkron dengan komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian iklim, seperti Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), strategi FOLU Net Sink 2030, dan Perjanjian Paris. Setiap kebijakan yang berbasis hutan, termasuk skema perdagangan karbon dan program restorasi, harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis hak.
Ketujuh, keterbukaan informasi publik harus dijamin. Masyarakat berhak mengetahui informasi penting seperti data perizinan, peta kawasan, dokumen AMDAL, rencana kerja, hingga data konflik kehutanan. Transparansi adalah prasyarat mutlak untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tumpang tindih kepentingan.
Kedelapan, rencana pemerintah untuk membuka hingga 20 juta hektare kawasan hutan, sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045, harus ditinjau ulang secara kritis. Ia bilang, kebijakan ini sangat berisiko terhadap wilayah-wilayah konservasi tinggi dan ruang hidup masyarakat.
“Karena itu, mekanisme pengawasan yang berbasis FPIC, kajian ekologis yang komprehensif, dan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat harus dimasukkan dalam UU sebagai sistem pengendalian yang ketat,” pungkasnya.

Momentum Mengakhiri Warisan Kolonial
Anggi Putra Prayoga, Juru kampanye Forest Watch Indonesia mengatakan, negara tidak boleh lagi mempertahankan paradigma kolonial yang melihat hutan semata sebagai komoditas dan milik negara. Saatnya, katanya, menempatkan hutan sebagai ruang hidup, dan mengakui peran serta hak masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga utama ekosistem hutan.
Anggi bilang, revisi UU Kehutanan harus menjadi titik balik dalam pengelolaan hutan Indonesia. Ia juga mengingatkan, tanpa perubahan substansial, Indonesia akan gagal memenuhi target penurunan emisi dari sektor Forestry and Other Land Uses (FoLU).
“UU Kehutanan harus diubah secara mendasar. Saat ini, ia sudah tidak lagi relevan menghadapi ancaman kerusakan hutan yang mencapai rata-rata 689 ribu hektare per tahun, apalagi dalam upaya perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat,” ujar Anggi Putra Prayoga.
Anggi menegaskan tiga pilar utama yang harus menjadi fondasi revisi UU ini. Pertama, perlunya pembaruan total terhadap paradigma penguasaan hutan oleh negara. Selama ini, klaim Kementerian Kehutanan atas 106 juta hektare daratan sebagai kawasan hutan negara dilakukan secara sepihak.
Padahal, kata Anggi, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011, ada empat tahapan penting dalam pengukuhan kawasan hutan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Namun dalam praktiknya, proses penataan batas sering kali dilewati, mengabaikan legitimasi masyarakat adat dan lokal. Bahkan, dalam satu tahun terakhir, anomali penetapan kawasan hutan melonjak hingga 20 kali lipat.
Kedua, RUUK harus berani menolak berbagai bentuk kamuflase pembangunan yang mengatasnamakan keberlanjutan, seperti program swasembada pangan dan energi, yang dalam praktiknya justru melegitimasi perusakan hutan secara sistematis dan pengingkaran hak rakyat.
Ketiga, RUUK harus secara eksplisit mengadopsi dan mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi—khususnya Putusan MK No. 34, 35, 45, dan 95—yang menjamin pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka, serta perlindungan dari praktik perizinan ekstraktif yang merusak dan menyingkirkan.
Riyono, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, turut menekankan pentingnya revisi yang berpihak pada keadilan masyarakat adat dan implementasi nyata dari putusan MK, sembari mendorong integrasi antara pengelolaan hutan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Suara-suara dari berbagai wilayah pun memperkuat urgensi perubahan. Raden dari WALHI Kalimantan Selatan menegaskan bahwa selama paradigma kolonial tetap digunakan—yang menjadikan hutan sebagai milik negara—Masyarakat Adat Meratus akan terus dikorbankan demi kepentingan izin ekstraktif.
“RUUK harus menjamin keadilan ekologis dan pengakuan penuh atas hak masyarakat adat yang wilayahnya dijadikan kawasan hutan tanpa persetujuan,” ujarnya.
Baca juga: Pisau Bermata Dua Penertiban Kawasan Hutan
Dari Kalimantan Barat, A. Syukri dari Link-Ar Borneo menyoroti bahwa keberadaan hutan tidak otomatis menjamin kesejahteraan, karena dikuasai logika industri dan monokultur. “Hutan Tanaman Industri bukan hutan, tapi kebun industri. Revisi ini bukan sekadar regulasi, tapi soal keadilan dan masa depan.”
Darwis dari Green of Borneo Kaltara memperingatkan bahwa tanpa jaminan perlindungan sosial, penerapan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan), dan pelaksanaan Putusan MK 35, revisi hanya akan memperluas konflik, kriminalisasi, dan kerusakan ekologis.
Afifuddin dari WALHI Aceh memperkuat argumen bahwa tanpa keberpihakan pada rakyat dan ekosistem, RUUK akan menjadi alat legalisasi krisis ekologis. Sulfianto dari Panah Papua menyebut bahwa pendekatan eksploitatif tanpa transparansi dan persetujuan masyarakat hanya akan mewariskan bentuk baru dari penjajahan, bukan pembangunan.
Dari Jambi, Oscar Anugrah menyingkap bagaimana transisi energi dalam konsesi kehutanan justru dijadikan kedok perampasan hutan dan penggusuran kebun rakyat. “RUUK harus menjamin agar narasi hijau tidak digunakan untuk mengabaikan hak ulayat dan merampas ruang hidup.”
Hal serupa terjadi di Gorontalo, di mana investasi monokultur dan bioenergi terus menyingkirkan masyarakat lokal. “RUUK seharusnya menjadi koreksi atas warisan ketimpangan kolonial, bukan memperkuatnya atas nama transisi energi global,” ujar Defri Setiawan dari WALHI Gorontalo.
Zul dari KORA Maluku menekankan pentingnya menghapus bias pulau besar dalam kebijakan kehutanan. Ia mencontohkan proyek biomassa di Pulau Buru yang menggusur ruang hidup masyarakat. “Masyarakat adat harus diakui bukan hanya sebagai pihak yang diajak berpartisipasi, tetapi sebagai pemilik sah hutan yang dirawat secara turun-temurun.”
Sementara itu, Faizal Ratuela dari WALHI Maluku Utara mengingatkan bahwa ketika negara menjadikan pulau-pulau kecil dan tak berpenghuni sebagai lokasi ekspansi proyek nasional, maka bukan hanya hutan yang dikorbankan, tapi juga identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat di tengah krisis iklim dan ancaman gempa.
Pandangan akademik turut memperkuat argumen perlunya reformasi besar dalam tata kelola hutan. Dr. Andi Chairil Ichsan dari Universitas Mataram menyebut bahwa RUUK bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi harus mencerminkan pemahaman ulang atas makna hutan, pembagian kekuasaan secara adil, dan tata kelola yang berorientasi pada keadilan sosial-ekologis.
Senada dengan itu, Dessy Eko Prayitno, dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus menjadi roh dari UU Kehutanan yang baru. “Dari proses pengukuhan, perizinan, pengawasan, hingga penegakan hukum, semua harus menjunjung tinggi pengakuan hak masyarakat,” pungkasnya.
Tulisan ini pertama kali terbit di situs Mongabay Indonesia dalam versi sudah sunting. Untuk membacanya, silahkan klik di sini.
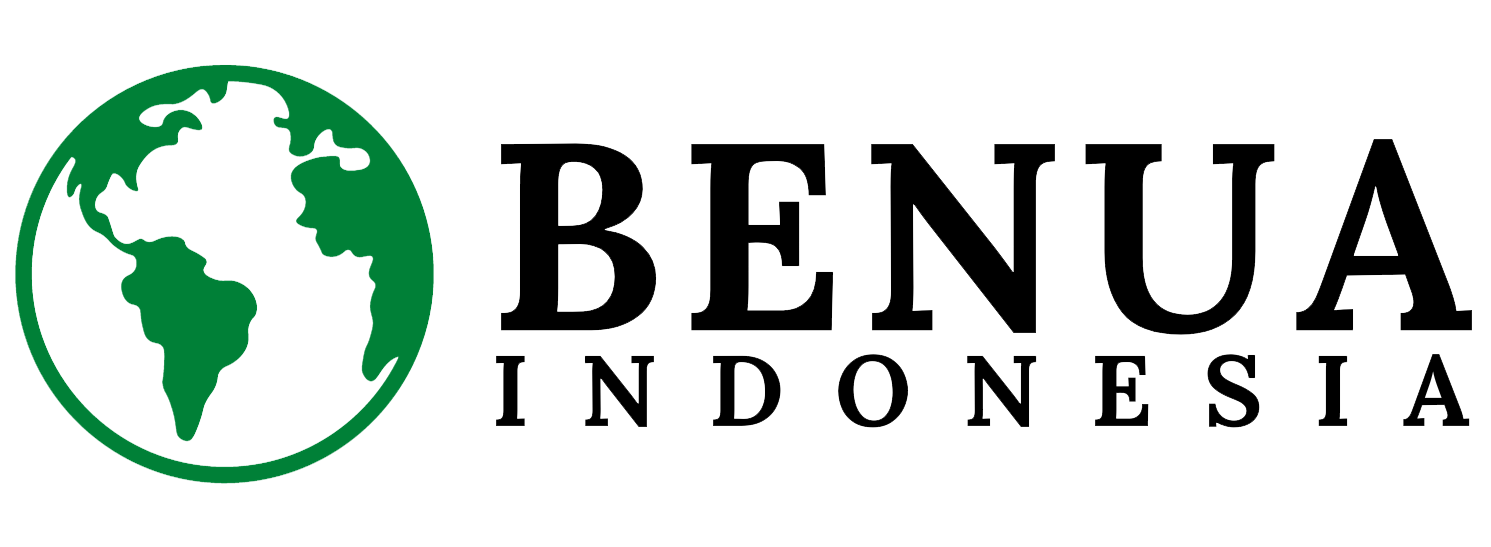











Leave a Reply
View Comments