Keputusan ini disambut meriah. Pemerintah menyebutnya sebagai “langkah strategis” menuju kemandirian ekonomi dan penguatan posisi diplomatik di kancah global. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dan dominasi lembaga keuangan Barat, BRICS dipandang sebagai jalan menuju tatanan baru yang lebih adil, lebih setara, lebih “selatan.”
Namun, di balik euforia diplomatik, muncul pertanyaan mendasar: apakah keanggotaan Indonesia di BRICS benar-benar membuka jalan menuju kemandirian dan keberlanjutan? Ataukah justru menjadi jebakan baru—ketika investasi besar datang membawa janji pertumbuhan, namun meninggalkan jejak luka ekologis?
Janji Selatan, Bayang-bayang Ketergantungan
Sebagai negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam, Indonesia tentu memiliki alasan untuk optimis. BRICS menjanjikan akses pada New Development Bank (NDB), sumber pendanaan alternatif untuk infrastruktur, transisi energi, dan teknologi digital—tanpa syarat politik ketat seperti yang biasa diterapkan oleh IMF atau Bank Dunia.
Kerja sama Selatan-Selatan ini kerap dielu-elukan sebagai bentuk solidaritas ekonomi baru, sebuah upaya membangun sistem global yang lebih inklusif, di mana negara-negara berkembang memiliki suara lebih besar dalam menentukan arah pembangunan.
Baca juga: Ketika AI Mengancam Bumi: Dimensi Baru Keamanan Lingkungan Global
Namun, sejarah panjang pembangunan global mengajarkan satu hal: hubungan ekonomi jarang benar-benar setara. Dalam perspektif teori ketergantungan (dependency theory), aliran modal dan teknologi dari luar sering kali menempatkan negara berkembang dalam posisi subordinat. Mereka memang tumbuh, tapi dalam struktur yang dibentuk oleh kepentingan eksternal.
BRICS boleh saja disebut kerja sama yang adil, tapi dalam praktiknya, negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar—seperti Tiongkok dan India—tetap menjadi pengendali utama. Indonesia memang memperoleh modal dan akses pasar, tetapi siapa yang menentukan arah industri? Siapa yang menikmati nilai tambah? Dan siapa yang harus menanggung risiko ekologis?
Hijau di Atas Kertas, Abu-abu di Lapangan
BRICS mengusung narasi pembangunan hijau: transisi energi, hilirisasi nikel, kendaraan listrik. Semuanya terdengar menjanjikan di atas kertas. Namun, dalam ekonomi politik lingkungan, kita tahu: pembangunan tidak pernah netral secara ekologis. Di balik setiap proyek “berkelanjutan” tersimpan relasi kuasa dan kepentingan.
Ambil contoh ekspansi pertambangan nikel di Raja Ampat. Proyek yang diklaim sebagai bagian dari rantai pasok energi bersih justru memicu deforestasi, pencemaran laut, dan kerusakan terumbu karang. Atas nama energi hijau global, kawasan tropis yang menjadi paru-paru dunia dikorbankan.
Inilah paradoks hijau—green paradox—di mana proyek yang diklaim ramah lingkungan justru memperpanjang logika eksploitatif kapitalisme ekstraktif. Narasi hijau menjadi kosmetik baru bagi ekonomi berbasis ekstraksi.
Baca juga: Mediasi Buntu: Bank Mandiri Tetap Bantah Danai Perusahaan Perusak Lingkungan
Akibatnya, masyarakat adat kehilangan tanah, nelayan kehilangan ruang tangkap, dan perempuan menghadapi beban ganda: dari kerusakan lingkungan hingga tergerusnya ekonomi lokal. Di tengah realitas ini, istilah “pembangunan berkelanjutan” kehilangan makna. Ia menjadi slogan yang menutupi ketimpangan dan penderitaan di akar rumput.
Masalah ini bukan semata persoalan teknis atau tata kelola, melainkan juga politik pengetahuan: siapa yang berhak mendefinisikan makna pembangunan, siapa yang dianggap penting, dan siapa yang dikorbankan?
BRICS, Geopolitik, dan Pusaran Kepentingan
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga memuat dimensi geopolitik yang tidak bisa diabaikan. BRICS bukan sekadar forum ekonomi, melainkan simbol pergeseran kekuasaan global. Ia menantang dominasi Barat dan menawarkan visi multipolaritas dunia di mana kekuatan-kekuatan baru muncul dari Selatan.
Namun idealisme multipolar itu juga menyimpan arena persaingan. Tiongkok ingin memperluas pengaruh di Asia, Rusia mencari sekutu di tengah sanksi, dan India berupaya menjaga keseimbangan keduanya. Indonesia kini berdiri di tengah pusaran tersebut: berpegang pada prinsip bebas-aktif, tetapi menghadapi tekanan ekonomi dan diplomatik yang semakin kompleks.
Baca juga: Perempuan dan Masa Depan Terhadap Lingkungan
Pertanyaannya: sejauh mana Indonesia bisa mempertahankan otonomi kebijakan nasional di tengah interdependensi global seperti ini? Proyek-proyek besar yang dibiayai NDB mungkin mendorong pembangunan jangka pendek, tetapi juga berisiko menimbulkan ketergantungan utang atau bahkan bentuk baru dari neo-kolonialisme ekonomi.
Dalam konteks ini, BRICS bukan hanya keputusan ekonomi, tetapi juga ujian bagi diplomasi dan kedaulatan Indonesia.
Mendorong Pertumbuhan yang Adil dan Ekologis
Agar peluang yang ditawarkan BRICS tidak berubah menjadi perangkap baru, Indonesia perlu membangun pendekatan yang berlandaskan pada realisme ekologis dan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Beberapa langkah penting yang perlu ditempuh, yakni: Perkuat regulasi dan akuntabilitas lingkungan. Setiap proyek, terutama di sektor energi dan pertambangan, harus tunduk pada standar keberlanjutan yang ketat. Audit independen, pelaporan berkala, dan partisipasi publik yang bermakna adalah kunci agar pembangunan tak hanya bersih secara administratif, tetapi juga adil secara ekologis.
Berikutnya: Diversifikasi mitra dan sumber pendanaan. Ketergantungan pada satu poros ekonomi, sekalipun menjanjikan, hanya mempersempit ruang gerak. Kerja sama lintas kawasan—dengan ASEAN, Uni Eropa, hingga Afrika—akan memperluas ruang negosiasi dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam sistem multipolar.
Baca juga: Kontribusi Pohon Alpukat & Pohon Jambu Biji Dalam Keberlanjutan Lingkungan
Selanjutnya; Dorong transparansi dan keterlibatan masyarakat. Pembangunan tak boleh “untuk rakyat tapi tanpa rakyat.” Konsultasi publik, pelibatan masyarakat adat, dan perlindungan terhadap pembela lingkungan harus dijamin. Transparansi bukan sekadar data terbuka, tapi juga keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan.
Terakhir; Bangun diplomasi hijau yang progresif. Keanggotaan BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan tata kelola lingkungan global yang lebih adil. Indonesia dapat memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan global dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di tingkat domestik.
Tanpa langkah-langkah seperti ini, kerja sama ekonomi global hanya akan mengulang pola lama: pertumbuhan yang dibayar dengan penderitaan dan krisis ekologis.
Antara Utopia dan Realitas
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memang membuka banyak peluang: akses pendanaan alternatif, diversifikasi ekonomi, dan penguatan posisi diplomatik. Namun, di balik peluang itu, tersimpan tantangan serius: bagaimana memastikan bahwa kerja sama ini memperkuat kemandirian nasional, bukan menjerumuskan Indonesia ke dalam ketergantungan baru.
Pertanyaannya kini: apakah Indonesia siap memimpin arah pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyatnya sendiri?
Optimisme tanpa kritik bisa menjelma utopisme: keyakinan bahwa pertumbuhan otomatis membawa kemajuan sosial. Padahal, pembangunan sejati menuntut kesadaran kritis terhadap relasi kuasa, ketimpangan, dan dampak ekologis yang ditimbulkannya.
Baca juga: Masa Depan Lingkungan Hidup Suram di Tangan Kabinet Merah Putih
Indonesia memiliki peluang untuk menjadi contoh bagi dunia Selatan: bahwa negara berkembang bisa menempuh jalannya sendiri—bukan sekadar meniru model pertumbuhan negara besar, tetapi membangun sistem ekonomi yang berpihak pada manusia, melindungi lingkungan, dan menjaga kedaulatan atas sumber dayanya.
Pada akhirnya, BRICS bukan soal siapa yang paling kuat secara ekonomi, tetapi siapa yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan, keadilan, dan keberlanjutan. Di titik inilah masa depan Indonesia akan diuji: sebagai aktor yang menentukan arah perubahan global, atau sekadar penonton dalam panggung yang ditulis oleh kepentingan negara lain.
Redaksi menerima artikel opini dengan panjang cerita minimal 700 kata, dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail redaksibenua@gmail.com disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat.
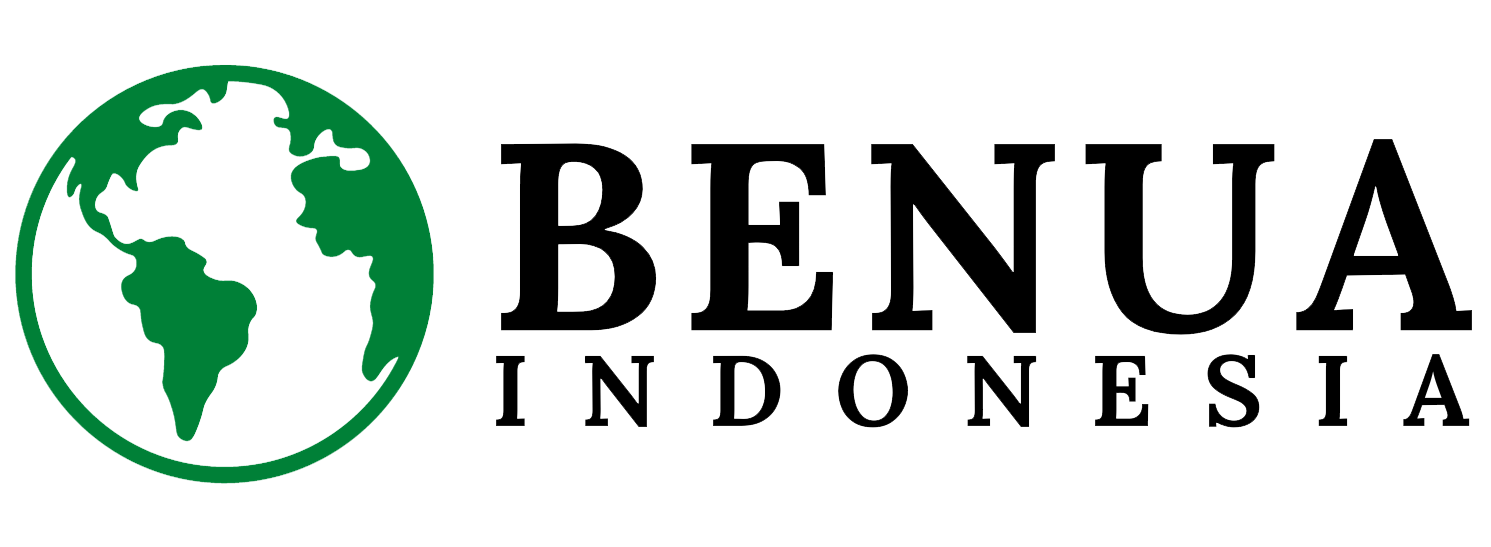













Leave a Reply
View Comments