Konferensi Tingkat Tinggi Asia Zero Emission Community (AZEC) yang digelar di Kuala Lumpur pada 28 Oktober 2025 lalu, jaringan organisasi masyarakat sipil Indonesia menyatakan penolakannya terhadap inisiatif AZEC.
Program ini dinilai justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil melalui “solusi palsu” yang membahayakan lingkungan, mengancam keselamatan komunitas, dan berisiko menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah Jepang dan Indonesia untuk berkomitmen pada transisi energi yang cepat, adil, dan merata, serta menjamin partisipasi bermakna dari masyarakat lokal dan kelompok sipil dalam proses transisi yang demokratis dan berpihak pada keadilan iklim.
Sejak awal, jaringan masyarakat sipil Indonesia telah menyuarakan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC yang dipimpin Jepang melalui strategi Green Transformation (GX), di mana sebagian besar proyeknya direncanakan berlangsung di Indonesia.
Pada 20 Agustus 2024, bertepatan dengan Pertemuan Tingkat Menteri AZEC ke-2 di Jakarta, sebanyak 41 organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan petisi penolakan terhadap arah dan isi inisiatif tersebut.
Organisasi masyarakat sipil menyoroti pelaksanaan AZEC yang melanggar prinsip demokrasi karena minim transparansi dan keterbukaan informasi, serta tidak melibatkan masyarakat secara bermakna.
AZEC justru mendorong penggunaan teknologi yang memperpanjang ketergantungan pada energi fosil — alih-alih menyelesaikan krisis iklim, langkah ini justru memperburuk penderitaan masyarakat terdampak.
Selain berisiko tinggi terhadap keselamatan lingkungan dan komunitas, AZEC juga berpotensi mendorong perampasan lahan dan ruang laut, serta mempercepat deforestasi di berbagai wilayah Indonesia.
Di tengah ketidakpastian ekonomi, skema pembiayaan AZEC bahkan dapat meningkatkan risiko beban utang (debt distress) yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Dwi Sawung, Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI, menyebut AZEC sebagai bentuk baru kolonialisme energi yang mengabaikan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Baca juga: Kolonialisme, Ruang dan Transisi Energi
Menurutnya, AZEC bukan solusi transisi energi yang adil. Ia menyamarkan kepentingan korporasi dan negara industri sebagai upaya dekarbonisasi, padahal yang terjadi adalah greenwashing sistemik.
“Transisi energi harus berangkat dari kebutuhan dan hak masyarakat, bukan dari skema investasi yang mengekalkan ketimpangan dan kerusakan ekologis,” tegas Sawung.
Riski Saputra, Peneliti Lingkungan AEER, menilai bahwa jika AZEC benar-benar serius mendukung transisi energi di Indonesia, arah kebijakan seharusnya difokuskan pada sistem energi berkelanjutan.
“Fokusnya harus pada pengembangan smart grid dan sumber energi bersih seperti surya dan angin,” ujar Riski
Ia bilang, AZEC juga seharusnya mendukung pensiun dini PLTU, bukan memperpanjang operasionalnya melalui solusi palsu seperti co-firing dan CCS/CCUS yang justru memperburuk keadaan.
Al Farhat Kasman, Juru Kampanye JATAM, menyebut AZEC sebagai wajah baru kolonialisme ekstraktif. Pasalnya, AZEC tidak hadir sebagai solusi atas krisis, tetapi sebagai perpanjangan kolonialisme ekstraktif.
Ia menegaskan, Investasi atas nama rendah karbon menyimpan jebakan utang, memperparah kerusakan lingkungan melalui ekstraksi sumber daya seperti panas bumi dan mineral kritis, serta menambah penderitaan masyarakat di wilayah operasi.
“Kesepakatan pemerintah Indonesia di bawah AZEC menunjukkan keberpihakan negara kepada pemodal,” ujarnya.
Wishnu Utomo, Direktur Advokasi Tambang CELIOS, menilai pendekatan AZEC dalam mitigasi krisis iklim keliru dan kontraproduktif.
Menurutnya, banyak proyek yang mereka danai justru berupa solusi palsu yang berbahaya bagi lingkungan dan sosial.
“Transisi energi seharusnya menjadi momentum memulihkan kehidupan masyarakat yang rusak akibat eksploitasi industri besar, bukan memperluas dampaknya,” tegas Wishnu.
Baca juga: Oligarki Membajak Transisi Energi di Bisnis Biomassa
Ia menambahkan bahwa langkah utama seharusnya memperkuat perlindungan lingkungan dan sosial agar transisi benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan.
Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mengungkapkan bahwa portofolio AZEC lebih banyak mendukung infrastruktur energi fosil dibanding energi terbarukan.
Menurut laporan Zero Carbon Analytics (2024), hanya 11% dari 158 Nota Kesepahaman (MoU) AZEC terkait energi surya dan angin, sementara 35% (56 MoU) melibatkan teknologi bahan bakar fosil seperti LNG, co-firing amonia, dan CCS.
“Dukungan AZEC terhadap co-firing PLTU, CCS/CCUS, dan gas fosil hanya memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan menjauhkan dari dekarbonisasi yang adil,” jelas Yuyun.
Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia, menilai pendekatan Jepang melalui AZEC justru menghambat komitmen global penanganan krisis iklim.
Melalui AZEC, kata dia, Jepang masih menyalurkan pembiayaan untuk solusi palsu ke negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.
“Di bawah kepemimpinan baru, seharusnya Jepang memperkuat dukungan terhadap energi terbarukan — bukan membiayai proyek yang memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil,” ujarnya.
Abdul Baits, dari Divisi Kajian dan GIS WALHI Jakarta, menyoroti bahwa proyek-proyek AZEC seperti co-firing biomassa, hidrogen, dan amonia di pembangkit berbasis fosil hanyalah kamuflase untuk memperpanjang umur batu bara dan gas.
Ia bilang, proyek-proyek seperti di Suralaya, Lontar, dan Muara Karang bukan solusi iklim, melainkan strategi memperpanjang penggunaan batu bara.
“Dampaknya, warga Jakarta akan terus menghadapi ancaman polusi udara yang membahayakan kesehatan dan kualitas hidup,” pungkasnya.
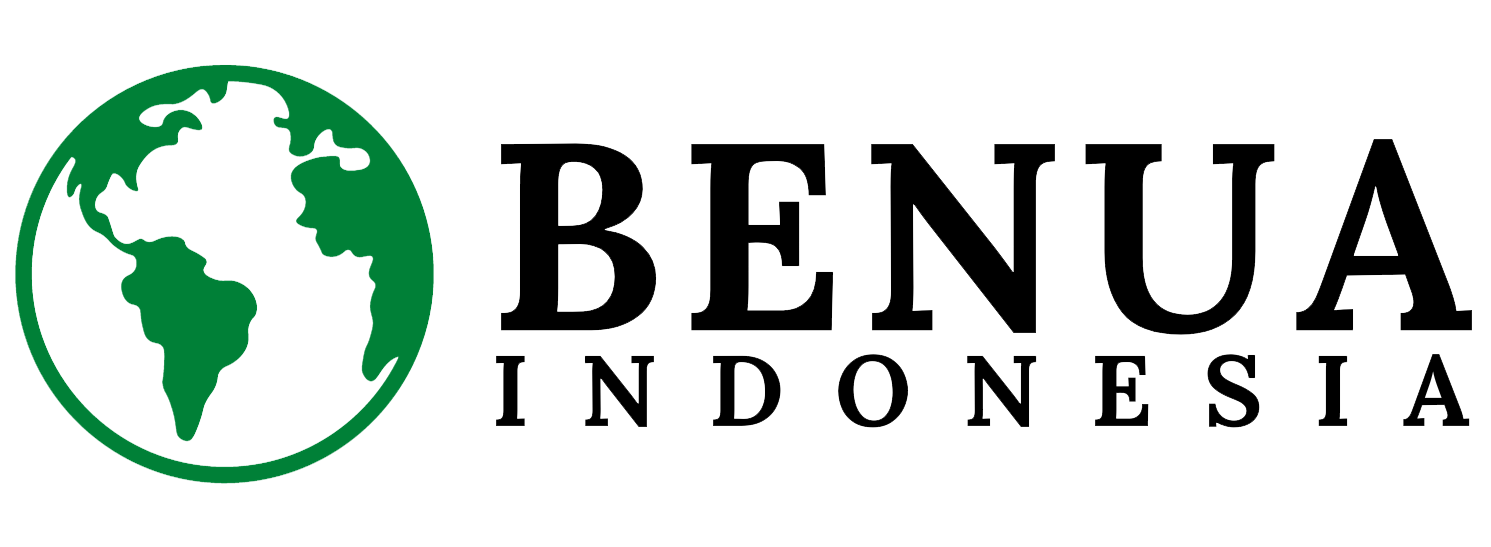












Leave a Reply
View Comments