TREN kehilangan hutan di Indonesia kembali melonjak dalam tiga tahun terakhir, membalikkan capaian positif yang sempat diraih sepanjang 2017 hingga 2021. Temuan terbaru Forest Declaration Assessment (FDA) yang dipublikasikan pada 13 Oktober 2025 menyimpulkan: dunia gagal menepati janji untuk menahan laju deforestasi. Indonesia menjadi cermin paling gamblang dari kegagalan itu.
Selama empat tahun, Indonesia sempat dipuji sebagai pionir penurunan deforestasi global. Namun, keberhasilan itu kini terkikis. Di satu sisi, Indonesia menjual citra hijau di panggung internasional. Di sisi lain, kebijakan dalam negeri justru membuka jalan bagi kerusakan baru atas nama pembangunan dan investasi.
“Pemerintah tampak ingin memelihara citra hijau di luar negeri, tetapi di dalam negeri, kebijakan seperti Food and Energy Sovereignty Plan dan pelonggaran izin tambang menunjukkan arah sebaliknya,” ujar Hilman Afif, juru kampanye Yayasan Auriga Nusantara.
Retorika Hijau, Realita Abu-abu
Lonjakan deforestasi disebut menjadi alarm keras atas rapuhnya komitmen menuju target FOLU Net Sink 2030—sebuah janji Indonesia untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Target itu, menurut aktivis, kian terdengar seperti retorika kosong jika hutan alam tersisa tak dilindungi secara nyata, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar.
Langkah pencabutan empat izin tambang di Raja Ampat pada awal 2025 sempat disebut sebagai sinyal perubahan. Namun kenyataannya, langkah tersebut hanya menyentuh permukaan. Data menunjukkan, masih terdapat 381 izin pertambangan aktif di 289 pulau kecil, mencakup wilayah seluas 921 ribu hektare yang mengancam ekosistem pesisir dan masyarakat lokal.
Baca juga: TFFF: Solusi untuk Hutan atau Bentuk Kapitalisme Hijau?
FDA mencatat, sektor pertanian permanen menjadi penyumbang utama deforestasi global, menyumbang hingga 86 persen. Situasi ini tercermin di Indonesia—di mana ekspansi kebun sawit, kayu, dan kini hutan tanaman energi kian mendesak kawasan hutan alam. Di Gorontalo, misalnya, proyek hutan energi berkembang pesat akibat kombinasi kebijakan nasional dan dorongan pasar biomassa global.
Ironisnya, ekspor biomassa dari Indonesia ke Jepang melonjak tajam antara 2021–2024. Energi bersih yang diklaim “ramah lingkungan” di satu negara, justru dibangun di atas kehancuran ekologis negara lain.
Transisi Energi, Tambang Baru, Luka Lama
Selain biomassa, ambisi global terhadap nikel—komoditas utama baterai kendaraan listrik—juga memperparah tekanan terhadap hutan Indonesia, terutama di kawasan timur. Industri ini memperluas tambang di tengah klaim transisi energi bersih. Padahal, hutan tropis kembali dikorbankan untuk mimpi kendaraan bebas emisi.
“Paradoks ini menunjukkan bahwa transisi energi dunia masih menggantungkan diri pada praktik ekstraktif yang menghancurkan ekosistem dan komunitas lokal,” kata Timer Manurung, Ketua Yayasan Auriga Nusantara.
Baca juga: Revisi UU Kehutanan Harusnya jadi Momentum Benahi Tata Kelola
Timer menyebut, program Food and Energy Sovereignty Plan yang membuka 481 ribu hektare hutan di Merauke menjadi contoh paling telanjang bahwa deforestasi bukan lagi akibat kelalaian teknokratis, melainkan keputusan politik yang sadar dan sistematis.
Alih-alih memperkuat perlindungan hutan alam, pemerintah justru memperluas izin agroindustri di kawasan yang menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Ketimpangan dalam penegakan hukum juga memperparah krisis. Negara dinilai lebih cepat menindak petani kecil dan masyarakat adat ketimbang korporasi besar penyebab utama deforestasi industri.
“Banyak masyarakat adat yang justru menjaga hutan, malah dikriminalisasi dan digusur,” ujar Timer.
Komitmen di Panggung, Penghianatan di Lapangan
Lebih jauh, Timer menilai akar persoalan bukan hanya lemahnya tata kelola, tapi sistem ekonomi-politik yang secara struktural menempatkan hutan sebagai korban permanen dari ambisi pertumbuhan.
“Permintaan global atas komoditas berisiko tinggi seperti sawit, kayu, biomassa, dan nikel terus tumbuh tanpa mekanisme uji tuntas yang memadai. Negara-negara importir menuntut komoditas bebas deforestasi, tetapi menutup mata terhadap jejak kerusakan di negara produsen,” katanya.
Indonesia kini berada di persimpangan tajam: antara mempertahankan komitmen iklim yang kerap dikibarkan di forum internasional, atau memilih jalur eksploitasi lingkungan demi mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
“Komitmen hijau yang dibangun di atas abu hutan tropis bukanlah solusi, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bumi,” tegas Timer.
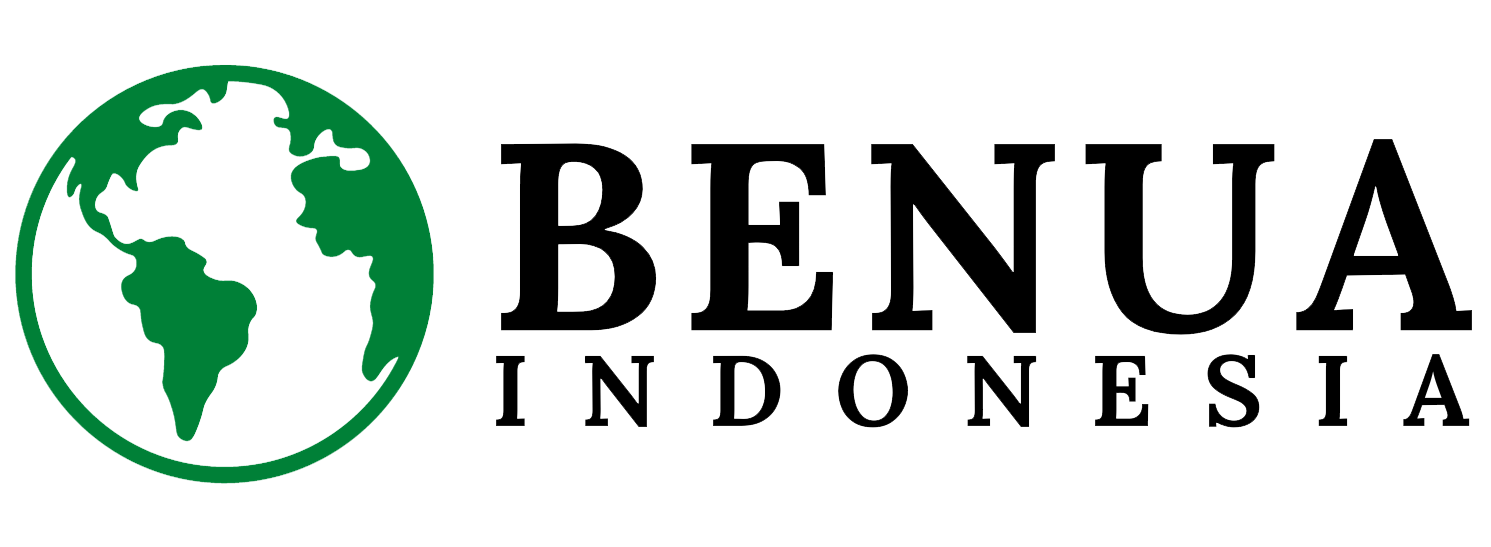











Leave a Reply
View Comments