- Peringatan Hari HAM Internasional 2025 di Desa Wiangun, Buol, berlangsung sebagai ruang warga desa untuk bersuara atas kehilangan tanah, pencemaran air, kerentanan pangan, dan intimidasi akibat ketidakadilan struktural, bukan sebagai seremoni formal.
- Melalui kegiatan yang diinisiasi Jaringan Jaga Deca, FPPB, dan LBH Progresif Buol, warga mengaitkan pengalaman hidup mereka dengan prinsip HAM yang selama ini terabaikan, terutama dalam konflik agraria dan skema kemitraan perkebunan yang merugikan petani.
- Kisah-kisah petani dan perempuan menegaskan bahwa ekspansi perkebunan, lemahnya pengawasan negara, serta keberpihakan hukum pada korporasi telah merusak lingkungan, layanan dasar, dan rasa aman masyarakat.
- Dari Wiangun, warga menyampaikan pesan bahwa persatuan rakyat, pengetahuan HAM, dan perjuangan kolektif adalah kunci untuk melawan ketidakadilan struktural dan menuntut pemulihan hak asasi manusia yang bermartabat.
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2025 di Desa Wiangun, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, tidak berlangsung sebagai seremoni formal. Tidak ada panggung mewah, pidato pejabat, atau baliho ucapan simbolik. Yang hadir justru warga desa—petani, buruh kebun, perempuan, dan masyarakat yang hidup di sekitar perkebunan—membawa cerita tentang tanah yang hilang, air yang tercemar, pangan yang kian sulit diakses, serta rasa takut yang menyertai setiap upaya bersuara.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Jaringan Jaga Deca, bersama Forum Petani Plasma Buol (FPPB) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif Buol. Bagi para penyelenggara dan peserta, Hari HAM bukan sekadar peringatan kalender internasional, melainkan ruang untuk menautkan pengalaman hidup warga dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang selama ini terasa jauh dari desa.
Setiap tanggal 10 Desember, dunia memperingati lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, sebuah komitmen global bahwa setiap manusia dilahirkan setara dalam martabat dan hak. Namun di Buol, hak-hak itu sering kali hadir sebagai kehilangan. Hak atas tanah berubah menjadi konflik agraria berkepanjangan. Hak atas air bersih menjadi beban tambahan bagi perempuan. Hak atas pangan tergantikan oleh ketergantungan pasar. Hak untuk bersuara berhadapan dengan intimidasi dan ancaman kriminalisasi.
Tema yang diusung dalam peringatan tahun ini—“Memperkuat Persatuan Rakyat, Melawan Ketidakadilan Struktural, dan Menuntut Pemulihan Hak Asasi yang Bermartabat”—lahir langsung dari kondisi tersebut. Buol menjadi contoh bagaimana ekspansi perkebunan skala besar, lemahnya pengawasan negara, dan relasi kuasa yang timpang bertemu dalam satu ruang, lalu menekan kehidupan masyarakat desa.

HAM yang Hadir dalam Kehilangan
Bagi warga Buol, HAM bukan istilah hukum yang dibaca di dokumen resmi. Ia hadir di jalan-jalan desa yang rusak, di kebun yang tak lagi bisa diakses, di sawah yang terendam pada musim hujan dan mengering pada musim kemarau, di sungai yang berubah warna dan terkontaminasi racun, serta di dapur yang makin sulit dipenuhi.
Dalam pembukaan kegiatan, fasilitator menegaskan bahwa HAM bukan pemberian negara dan bukan kemurahan hati perusahaan. HAM adalah hak yang melekat sejak manusia dilahirkan: hak atas tanah, air, pangan, pekerjaan layak, lingkungan hidup yang sehat, layanan dasar, dan kebebasan bersuara. Penegasan ini menjadi penting di wilayah yang selama bertahun-tahun warganya dibiasakan untuk menerima ketimpangan sebagai nasib.
Meski kegiatan berlangsung di bawah penjagaan aparat keamanan, fasilitator menekankan bahwa ruang diskusi ini adalah ruang aman. Peserta didorong untuk berbicara, berbagi pengalaman, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Ajakan ini bukan basa-basi. Bagi banyak warga Buol, berbicara tentang tanah, perkebunan, dan perusahaan berarti berhadapan dengan risiko sosial, tekanan psikologis, dan ancaman kriminalisasi.
Suasana kemudian menghangat ketika peserta meneriakkan yel-yel bersama. Seruan seperti “Landreforma—Tanah untuk Rakyat!”, “Pangan dan Air—Hak Seluruh Rakyat!”, “Kemitraan Merugikan—Kembalikan Tanah Kami!”, hingga “Bangun Persatuan—Lawan Ketidakadilan!” menggema di ruang pertemuan. Yel-yel ini bukan sekadar pemantik semangat, melainkan artikulasi politik warga atas situasi yang mereka alami.
Tanah, Air, dan Kemitraan yang Menjerat
Acara dilanjutkan dengan sesi speak out dari para peserta. Seorang petani plasma menceritakan bagaimana kebun yang dijanjikan sebagai sumber kesejahteraan justru menjadi sumber konflik berkepanjangan. Dalam skema kemitraan, petani kehilangan kendali atas tanahnya sendiri. Mereka tidak memiliki akses informasi yang setara, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan terjebak dalam perhitungan utang yang tidak transparan.
Bahkan, tanah yang mereka “mitrakan” kini terancam lepas sepenuhnya dari tangan mereka. “Awalnya kami dijanjikan hasil dan masa depan,” ujar seorang petani. “Sekarang kami tidak tahu lagi tanah itu milik siapa.”
Peserta lain, yang datang dari desa berbeda, mengungkapkan bagaimana ia selama ini diperalat oleh pengurus koperasi. Ia ditunjuk sebagai ketua kelompok tani dalam skema kemitraan, namun baru belakangan menyadari bahwa dirinya dan banyak anggota kelompoknya tidak tercantum sebagai peserta resmi. Nama-nama mereka tidak termuat dalam Surat Keputusan Bupati, padahal merekalah pemilik lahan secara turun-temurun dari orang tua mereka. Tanah dikelola, risiko ditanggung, tetapi pengakuan hukum tidak pernah diberikan.
Seorang perempuan dari Desa Wiangun mengisahkan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sehari-hari. Sungai yang dulu menjadi sumber utama air kini tidak lagi aman digunakan. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, warga terpaksa mengandalkan air tanah dengan kualitas buruk. Sementara untuk memasak dan konsumsi, mereka harus membeli air isi ulang—sebuah pengeluaran baru yang langsung menambah beban ekonomi keluarga.
Beban ini hampir tak pernah muncul dalam kebijakan, tetapi dirasakan setiap hari oleh perempuan. Ketika air bersih sulit diakses, perempuan harus berjalan lebih jauh, menghabiskan lebih banyak waktu, dan menghadapi risiko kesehatan. Hak atas air bersih, yang dijamin sebagai bagian dari hak atas standar hidup layak, berubah menjadi perjuangan harian.

Pola Konflik Agraria yang Berulang dan Sistemik
Konflik agraria menjadi pintu masuk paling jelas untuk memahami ketidakadilan struktural di Buol. Dalam paparan perwakilan Jaringan Jaga Deca, ditegaskan bahwa konflik-konflik ini bukan kasus terpisah, melainkan bagian dari pola yang berulang dan sistematis.
Pembukaan lahan kerap mendahului izin. Wilayah kelola warga diperlakukan seolah tanah kosong. Penguasaan tanah melampaui Hak Guna Usaha (HGU). Program revitalisasi perkebunan yang melibatkan ribuan petani dengan luasan sekitar 6.700 hektar justru terancam hilang karena penguasaan perusahaan atas nama kemitraan.
Janji plasma dan kemitraan dijadikan alat legitimasi, namun dalam praktiknya tidak pernah benar-benar menyejahterakan petani. Sebaliknya, skema ini menciptakan ketergantungan, menyingkirkan petani dari posisi subjek, dan menempatkan mereka sebagai objek dalam sistem produksi yang dikendalikan korporasi.
Hilangnya tanah bukan hanya soal kehilangan aset ekonomi. Ia berarti runtuhnya seluruh sistem kehidupan. Sebelum perkebunan monokultur masuk, banyak keluarga di Buol mengandalkan kebun campur—kelapa, ubi, sayur, buah, dan rempah—sebagai sumber pangan dan pendapatan. Sistem ini memberi ketahanan pangan dan kemandirian.
Ketika kebun digantikan oleh satu komoditas, ketergantungan pada pasar meningkat. Pangan yang dulu diproduksi sendiri kini harus dibeli. Biaya hidup naik, sementara pendapatan tidak pasti. Perubahan ini tidak pernah dihitung sebagai “biaya pembangunan”.
Kerusakan lingkungan memperparah kerentanan tersebut. Sungai-sungai sebagai sumber air utama mengalami penurunan debit, peningkatan sedimentasi, dan penurunan kualitas air.
Layanan Dasar, Intimidasi, dan Rasa Takut yang Dipelihara
Di banyak desa di Buol, persoalan layanan dasar memperlihatkan wajah lain dari ketidakadilan struktural yang selama ini dibiarkan berlangsung. Jalan desa rusak dan sulit dilalui, akses ke fasilitas kesehatan jauh, transportasi darurat nyaris tidak tersedia, sementara layanan publik hadir secara minim dan tidak merata. Dalam situasi konflik agraria yang berkepanjangan, kondisi ini justru semakin memburuk, seolah menjadi konsekuensi yang harus diterima warga yang hidup di wilayah konsesi.
Di saat yang sama, warga yang berani bersuara kritis menghadapi tekanan yang terus-menerus. Intimidasi tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik terbuka. Ia hadir sebagai ancaman halus, stigma sosial, pemanggilan aparat, hingga pembungkaman sistematis. Rasa takut ini membentuk ruang sunyi—ruang di mana pelanggaran HAM terjadi berulang kali tanpa dokumentasi memadai dan tanpa keadilan.
Sejumlah laporan dugaan pelanggaran hukum, termasuk kasus penganiayaan dan tindak kekerasan terhadap warga, telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun hingga lebih dari satu tahun berlalu, laporan-laporan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti. Sebaliknya, para petani justru berulang kali menerima panggilan polisi atas laporan dari pihak perusahaan, bahkan dalam kasus-kasus yang diduga kuat bersifat sepihak dan tidak berdasar.
Ketimpangan penanganan hukum ini memperlihatkan bagaimana aparat negara kerap hadir lebih cepat untuk melindungi kepentingan korporasi dibandingkan menjamin rasa aman warga. Hukum, yang seharusnya menjadi alat perlindungan, berubah menjadi instrumen tekanan. Dalam kondisi seperti ini, rasa takut bukan sekadar emosi individual, melainkan hasil dari struktur kekuasaan yang sengaja dipelihara. Namun, diam bukan akhir cerita.

Persatuan Rakyat dan Pengetahuan sebagai Alat Perlawanan
Di tengah tekanan tersebut, warga Buol membangun bentuk-bentuk perlawanan yang tidak selalu spektakuler, tetapi konsisten. Beberapa desa menghentikan panen perusahaan sebagai bentuk protes kolektif. Warga mempertahankan hulu sungai sebagai sumber air bersama. Organisasi petani independen seperti Forum Petani Plasma Buol (FPPB) dibentuk sebagai wadah konsolidasi.
Mereka memetakan wilayah secara mandiri, mendokumentasikan kerusakan, mengumpulkan bukti, dan menyusun strategi advokasi. Ini bukan tindakan sporadis, melainkan upaya sadar untuk mempertahankan ruang hidup dan hak asasi manusia.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Jaringan Jaga Deca menegaskan bahwa persatuan rakyat adalah fondasi utama melawan ketimpangan kuasa. Tanpa persatuan, pelanggaran HAM akan terus dinormalisasi atas nama investasi dan pembangunan.
Sementara itu, narasumber dari LBH Progresif Buol menyoroti pentingnya peningkatan pengetahuan hukum dan HAM di tingkat warga. Banyak pelanggaran dibiarkan terjadi karena warga tidak tahu bahwa apa yang mereka alami adalah pelanggaran hak.
“Pengetahuan adalah alat perlawanan,” tegasnya. Perjuangan HAM tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ia harus kolektif—melalui organisasi, advokasi bersama, pendokumentasian kasus, serta keberanian menggunakan jalur hukum dan tekanan publik.
Menuntut Pemulihan Hak yang Bermartabat dari Winangun
Diskusi mengerucut pada tuntutan pemulihan hak yang bermartabat. Warga menegaskan bahwa mereka tidak hanya menuntut ganti rugi material. Pemulihan berarti pengembalian kontrol atas tanah, pemulihan sungai dan hutan, jaminan air bersih dan pangan, perlindungan buruh, serta ruang aman bagi perempuan dan pembela lingkungan.
Dalam perspektif HAM, pemulihan berarti mengembalikan kemampuan warga untuk hidup aman, sehat, dan mandiri—bukan sekadar menutup kasus di atas kertas.
Peringatan Hari HAM Internasional 2025 di Desa Wiangun menunjukkan bahwa perjuangan HAM tidak lahir dari ruang-ruang elit. Ia tumbuh dari desa, dari cerita-cerita kecil yang disatukan menjadi suara kolektif.
Buol mungkin bukan satu-satunya wilayah dengan persoalan serupa. Namun dari Wiangun, warga menyampaikan pesan yang jelas: persatuan rakyat adalah kekuatan nyata. Ketidakadilan struktural bukan sesuatu yang abstrak—ia bisa dan harus dilawan. Dan pemulihan hak asasi manusia tidak boleh ditawar; ia harus dijalankan secara bermartabat.
Selama tanah masih dirampas, air masih tercemar, pangan makin sulit diakses, dan suara rakyat ditekan, maka Hari HAM akan selalu menjadi pengingat bahwa tugas negara belum selesai—dan perjuangan rakyat belum berakhir.
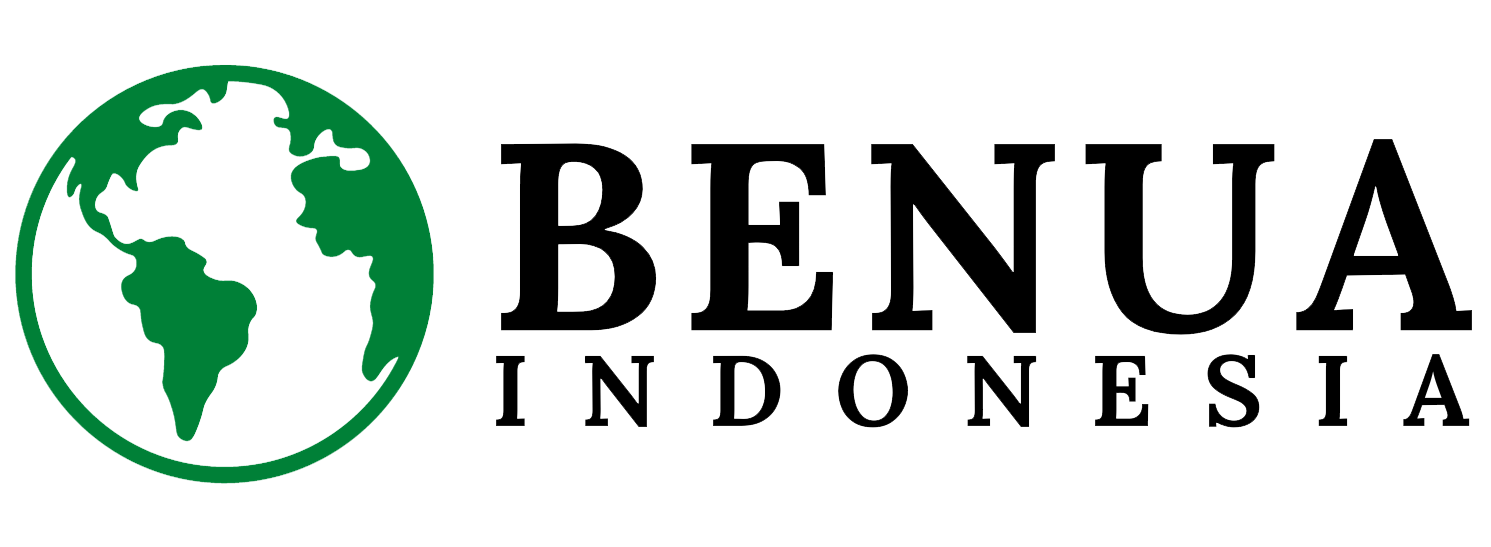












Leave a Reply
View Comments