- Transisi energi global berpotensi merusak ekologi dan hak-hak masyarakat adat jika tidak diimbangi dengan keadilan dan perlindungan hukum.
- Kasus Kabaena, Halmahera, dan Merauke menunjukkan bagaimana ambisi energi dan proyek strategis nasional menimbulkan pencemaran, perampasan tanah, dan degradasi lingkungan.
- Masyarakat adat sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, padahal mereka adalah penjaga hutan dan ekosistem.
- Keadilan iklim sejati hanya dapat tercapai dengan melibatkan masyarakat adat secara penuh, menghormati hak mereka, dan menempatkan mereka sebagai pusat strategi transisi energi.
Di tengah gegap gempita janji-janji iklim yang digaungkan para pemimpin dunia dalam ruang-ruang negosiasi COP30 di Belém, Brazil, nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
Dalam diskusi side event COP30 Centering Justice and Responsible Critical Minerals Governance di Ford Foundation Pavilion, suara-suara masyarakat sipil Indonesia berupaya menembus narasi besar tersebut, menyodorkan kenyataan bahwa di balik dorongan energi bersih, ada komunitas yang mempertaruhkan tanah, air dan hidupnya.
Cerita dari pulau kecil Kabaena di Sulawesi Tenggara merupakan bukti nyata bagaimana ekosida terjadi akibat ambisi hilirisasi nikel yang digaungkan pemerintah Indonesia, begitupun di Pomalaa Industrial Park. Kedua wilayah ini merupakan bagian dari rantai pasok produsen otomotif global seperti Volkswagen, Ford Motors, Tesla, BMW, BYD, dan lain-lain.
“Masyarakat Adat Bajau di Kabaena tak lagi bisa mencari ikan sebagai sumber penghidupannya. Air laut kini sudah berubah merah. Anak-anak sudah tak lagi berenang di sana. Laut yang dulu menjadi rumah kini berubah menjadi racun,” ungkap Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien dalam diskusi yang berlangsung di Belém, Brazil, Rabu (12/11/2025).
Riset Satya Bumi (2025) menunjukkan, dari hasil uji tes urine, masyarakat Kabaena terpapar nikel sebesar 5 hingga 30 kali lebih tinggi dibanding populasi umum, dan bahkan 1,5 hingga 10 kali lebih tinggi dari komunitas yang tinggal di dekat fasilitas industri nikel aktif. Bukan hanya nikel, urine masyarakat Kabaena mengandung logam berat berbahaya lain seperti kadmium, timbal dan seng yang tentunya berdampak sangat buruk bagi kesehatan.
Bukan hanya di Kabaena, Sulawesi Tenggara. Andi juga menunjukkan dampak tambang nikel yang dirasakan oleh suku Honganamayawa di Halmahera, Maluku Utara. “Untuk itu perlu kita mendorong dunia internasional untuk berhenti mengambil nikel dari pulau-pulau kecil dan menghentikan operasional perusahaan yang tidak bertanggung jawab,” tegas Andi.
Baca juga: Ironi Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Pangan dan Energi Nasional
Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat Albert Kwokwo Barume menyatakan, kekosongan perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Adat menjadi musabab persoalan ini.
“Saya melihat kecenderungan negara-negara ini seolah menahan diri untuk tidak memberikan hak-hak Masyarakat Adat lantaran kekosongan kerangka hukum nasional terkait HAM dalam masalah ini. Ini yang seharusnya dibahas dalam COP30,” jelas Barume dalam kesempatan yang sama.
Barume yang pernah meninjau langsung Proyek Strategis Nasional (PSN) Poco Leok pada Juli 2025 lalu menilai PSN dan industri ekstraktif di Indonesia dilakukan tanpa persetujuan awal, bebas dan berdasarkan informasi (free, prior and informed consent) dari Masyarakat Adat terdampak. Absennya persetujuan tersebut mengakibatkan perampasan tanah dan degradasi lingkungan serta memperparah pelanggaran hak asasi manusia.
Terpisah, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan keadilan iklim sebagai landasan utama dari kebijakan transisi energi. Menurutnya, transisi energi yang berkeadilan berarti berpindah ke energi terbarukan tanpa mengorbankan ruang hidup dan hak-hak masyarakat.
“Transisi yang benar harus melindungi hutan dan wilayah adat, menghentikan ekspansi energi fosil, serta memastikan masyarakat terlibat dan mendapat manfaat nyata dari perubahan itu. Jangan atas nama ‘transisi bersih’ kita mengambil tanah, merusak lingkungan, atau menyingkirkan warga dari kehidupannya,” kata Iqbal.
Bagi Greenpeace, keadilan iklim bukan sekadar soal mengurangi emisi gas rumah kaca melainkan juga memastikan kelompok rentan tidak menjadi korban kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite ekonomi. Partisipasi bermakna menjadi kunci dalam menciptakan keadilan iklim. Setiap langkah menuju energi bersih harus memperkuat perlindungan hak hidup rakyat dan menjamin masa depan yang aman bagi generasi mendatang.

Aktivis Papua Suarakan Krisis Hutan
Aktivis lingkungan asal Papua turut hadir dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 yang sedang berlangsung di Belém, Brasil. Keterlibatan mereka menandai minimnya respon pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hutan dan ruang hidup masyarakat adat di Tanah Papua.
Selain mengikuti rangkaian diskusi resmi, para aktivis lingkungan ini juga melakukan kunjungan solidaritas ke komunitas adat Ka’apor di wilayah Amazon, dan bergabung dalam aksi Flotilla.
Pengkampanye Yayasan Pusaka, Dorthea Wabiser, menjelaskan bahwa kunjungan ke Suku Ka’apor dilakukan sebagai bentuk solidaritas masyarakat adat lintas benua yang menghadapi ancaman serupa. Ka’apor dikenal sebagai komunitas yang berani menggugat kebijakan destruktif pemerintah Brasil dan perusahaan, termasuk gugatan terhadap Presiden Jair Bolsonaro atas dugaan ecocide.
“Kini wilayah adat Ka’apor kembali ditekan melalui ekspansi industri tebu, penebangan kayu, dan proyek karbon berskala besar,” katanya.
Selain berdiskusi dengan masyarakat Ka’apor, delegasi Papua juga mengikuti gerakan kolektif Flotilla. Aksi tersebut menggunakan armada besar yang mengantar lebih dari 5.000 perwakilan masyarakat adat dari 60 negara menuju lokasi COP30. Armada ini mencakup kapal-kapal ikonik seperti Yaku Mama (Ekuador), The Answer Caravan (Brasil) yang dipimpin tokoh adat Raoni Metuktire, serta Flotilla 4 Change.
Aksi sepanjang lebih dari 3.000 kilometer sungai Amazon itu menyerukan penghentian “solusi iklim palsu” dan mendesak negara-negara untuk menempatkan masyarakat adat sebagai pusat strategi iklim global. “Momen tersebut melambangkan kekuatan dan ketahanan masyarakat hutan, sebagai penjaga Amazon, suara mereka sangat penting bagi diskusi iklim global,” katanya.
Banyak masyarakat adat di belahan dunia lain serupa nasibnya. Keterlibatan dan suara mereka kerap diabaikan dalam negosiasi resmi. “Sungguh disayangkan banyak suara masyarakat adat tidak dilibatkan dalam negosiasi COP30, dan kami sangat merasakan hal ini sebagai orang Papua Barat. Hutan kami bukan untuk dinegosiasikan, hutan kami bukan bank anda,” ujarnya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merauke, Teddy Wakum, mengatakan di Tanah Papua, proyek strategis nasional di Merauke tak hanya merusak hutan dan ruang hidup masyarakat, tapi juga hadirnya aparat militer di sana menimbulkan ketegangan sosial. Hal ini akan mereka sampaikan dalam forum COP30.
“Ini proyek besar negara. Tapi bagi kami, apapun caranya akan kami tempuh, termasuk lewat mekanisme internasional, agar dunia tahu bahwa masyarakat adat Papua hari ini sedang menghadapi ketidakadilan,” kata Teddy.
Baca juga: Kolonialisme, Ruang dan Transisi Energi
Ia menilai kian mencoloknya paradoks antara diplomasi hijau Indonesia di luar negeri dan realitas kehancuran hutan di dalam negeri. “Di luar, Indonesia bicara soal perdagangan karbon dan pelestarian hutan. Tapi di Merauke, hutan masyarakat adat justru dibabat. Kalau serius ingin bicara iklim, hentikan proyek-proyek perusak hutan,” ujarnya.
Para aktivis itu juga akan membahas tentang kearifan lokal masyarakat adat yang telah terbukti menjaga dan memanfaatkan hutan secara bijak. “Kami yakin masyarakat adat dengan pengetahuan kearifan adat mereka, sejak lama mampu mengelola hutan, dibandingkan negara,” katanya.
Dalam berbagai pernyataan resmi di COP30, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mekanisme perdagangan karbon nasional dan regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) akan memberi manfaat nyata kepada masyarakat penjaga hutan. Pemerintah juga mengklaim penguatan pengakuan hutan adat melalui alokasi sekitar 1,4 juta hektare.
Namun menurut organisasi masyarakat sipil, kenyataan di lapangan justru berlawanan. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante, menyatakan bahwa negara terus mendorong konversi hutan skala besar demi kepentingan komersial.
“Negara cenderung berorientasi memanfaatkan hasil hutan untuk tujuan komersial yang terbukti merusak dan justru berperan sebagai driver of deforestation,” kata Franky.
Ia mencontohkan, di Merauke, Papua Selatan, pemerintah mengembangkan proyek strategis pangan, energi, dan air yang akan mengonversi sekitar 2 juta hektare kawasan hutan. Tahun 2025, SK Menteri Kehutanan telah melepaskan dan mengubah peruntukkan kawasan hutan di Papua, termasuk sekitar 490 ribu hektare untuk proyek food estate Merauke.
Pada September lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pun justru mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan kawasan tersebut dengan menargetkan total pembebasan lahan 1 juta hektare dengan melakukan perubahan tata ruang.
Menurut Franky, program tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa berkonsultasi dan bermusyawarah dengan masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mendiami wilayah tersebut.
“Pemerintah memandang hutan adat sebagai milik negara yang bebas dialihfungsikan. Ini menunjukkan pandangan kolonial yang masih hidup dalam kebijakan negara,” ujarnya.
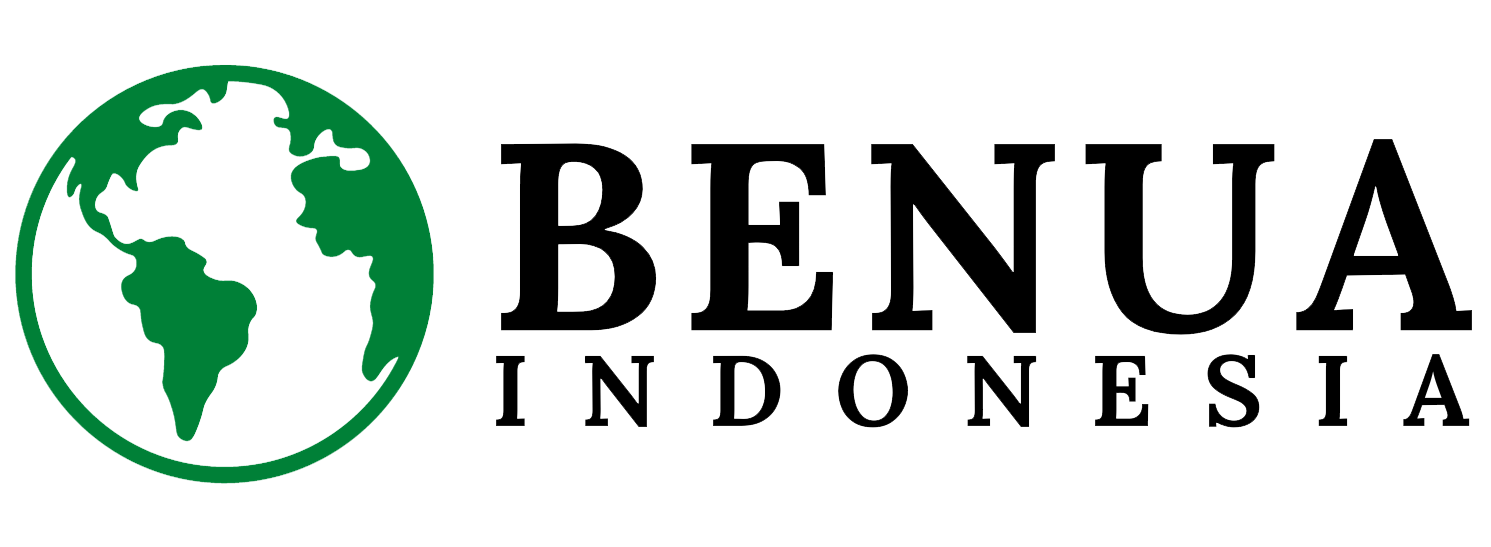












Leave a Reply
View Comments