- Industri fast fashion mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produksi massal dan konsumsi cepat, namun menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran air, udara, dan limbah tekstil yang masif.
- Di Indonesia, fenomena ini memperparah masalah lingkungan dan menekan industri lokal, sementara kesadaran daur ulang dan kebijakan berkelanjutan masih belum optimal.
- Komitmen internasional mulai mengarah pada ekonomi sirkular dan mode berkelanjutan, tetapi tantangan tetap besar, terutama bagi negara berkembang yang masih bergantung pada industri ekstraktif.
- Solusi membutuhkan regulasi ketat, inovasi lokal, serta perubahan pola konsumsi masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Berapa harga sesungguhnya dari sepotong pakaian murah yang berganti tren setiap pekannya? Di luar label diskon dan etalase toko, harga itu dibayar dengan air yang tercemar, udara yang kotor dan hutan yang hilang demi memuaskan ritme ekonomi global yang tak mengenal jeda.
Dalam era globalisasi, brand-brand internasional seperti H&M, Zara, Uniqlo dan SHEIN merilis koleksi baru setiap pekannya. Fenomena ini mendemokratisasi akses mode dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui volume produksi masif.
Namun di sisi lain, pola konsumsi sekali pakai dapat mengakumulasi dampak yang serius, yaitu penggunaan bahan baku dan energi yang berlebihan hingga sampah tekstil raksasa.
Pola konsumsi fesyen instan ini mempercepat degradasi lingkungan global, memicu krisis iklim, serta menggugah pertanyaan “Apakah kita harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempedulikan batas ekologis?”
Industri fashion telah meninggalkan tumpukan limbah tekstil dan polutan yang mengancam bumi. Industri ini merupakan konsumen air terbesar kedua dan bertanggung jawab atas 2-8% emisi karbon global.
Setiap tahunnya industri ini menyumbang 20% limbah air, khususnya dari proses pewarnaan tekstil. Limbah cair ini dinilai mengandung zat toksik yang mencemari ekosistem air dan kesehatan masyarakat lainnya.
Selain itu mikroplastik dari hasil pencucian pakaian yang berbahan polyester juga menyumbang sekitar 500.000 ton per tahunnya ke lautan. Gaya berpakaian yang sekali pakai juga menjadi kekhawatiran di sini. Pasalnya, sekitar 85% serat tekstil berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di seluruh dunia.
Di Indonesia, fenomena fast fashion memiliki dampak yang nyata. Indonesia masuk pada jajaran 10 besar produsen tekstil di dunia tetapi juga tingkat konsumsi yang relatif tinggi.
Baca juga: PP KEN 2025: Ambisi Energi Bersih Surut, Batubara Tetap Perkasa
Studi Bappenas mencatat bahwa rata-rata orang Indonesia cenderung membuang pakaiannya hanya dalam beberapa hari pemakaian.
Pada 2021, Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton pertahunnya dan hanya 0.3 juta ton yang telah didaur ulang. Fenomena “Thrifting” atau membeli baju bekas sebenarnya dapat menjadi solusi untuk meringankan jumlah limbah tetapi pada kenyataannya justru sebagian besar baju bekas dari negara asal tersebut menumpuk tanpa ada proses daur ulang memadai.
Dampaknya yang dirasakan bukan hanya pada limbah saja, produk fashion lokal atau UMKM dapat terjepit karena kalah bersaing dengan harga. Kondisi ini menegaskan bahwa selain regulasi yang ketat, kesadaran kolektif dan inovasi lokal juga dibutuhkan.
Dampak nyata dari fast fashion juga dirasakan di Sungai Citarum, Jawa Barat yang tercemar bahan kimia tekstil sehingga warga lokal menderita penyakit dermatitis kulit serta menganggu ekosistem sungai.
Selain itu, di Solo, Jawa Tengah terdapat kasus kebocoran gas di pabrik serat rayon sritex yang berakhir pada pencabutan perizinan pengoperasian. Meskipun demikian, pencemaran kualitas air dan udara yang menimbulkan penyakit dan matinya ikan di sungai Bengawan Solo tidak dapat terhindarkan.
Berbagai studi menegaskan bahwa industri fashion global menyumbang lebih dari 4% emisi gas rumah kaca dunia, bahkan bisa melebihi itu jika tidak cepat diatasi. Maka dari itu, agenda internasional saat ini mulai berfokus pada isu tersebut.
Pada tahun 2019, PBB membentuk Alliance for Sustainable Fashion yang bertujuan untuk menghentikan praktik industry fashion yang merusak lingkungan dan sosial.
Eropa sebagai pusat fashion dunia juga meluncurkan kebijakan berupa strategi sirkular yang memiliki target pada 2030, semua produk tekstil di Eropa harus bebas dari zat berbahaya, terbuat dari serat daur ulang, tahan lama serta dalam proses produksinya menghormati hak sosial dan lingkungan.
Dalam forum internasional seperti G20 dan GACERE (Global Alliance on Circular Economy), puluhan negara maju dan berkembang telah berkomitmen menjadikan ekonomi sirkular sebagai kerangka pembangunan, termasuk untuk industri fashion.
Baca juga: 5 Request Orang Muda Demi Bumi Lebih Bersih
Sedangkan dalam ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) 2025, ASEAN khususnya Indonesia bertekad menjadi pelopor pengelolaan sampah regional dengan menargetkan 100% sampah termasuk tekstil terkelola dengan baik pada 2029, serta menyerukan agar ASEAN memperjuangkan kesepakatan global untuk mengakhiri polusi plastik.
Sementara, ASEAN menyepakati pernyataan bersama untuk COP30 mengenai perubahan iklim dan menyusun ASEAN Center for Climate Change (ACCC) serta menetapkan taman lindung baru dan penghargaan kota berkelanjutan.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tantangannya ada pada merumuskan strategi pertumbuhan baru yang tidak mengorbankan sumber daya alam dan lingkungan. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah atau industri padat karya berenergi fosil harus diselaraskan dengan target keberlanjutan.
Ancaman kerusakan ekologis dari model ekstraktif mendorong lahirnya pemikiran “Degrowth” atau dengan kata lain pembatasan pertumbuhan. Gerakan ini menantang asumsi “pertumbuhan hijau” yang dominan, dengan argumen bahwa ekonomi tidak bisa terus menerus tumbuh di dunia yang penuh keterbatasan ini.
Para ahli menekankan, tanpa adanya regulasi kuat pada tata kelola SDA, kekayaan alam yang melimpah bisa menjadi jebakan kemiskinan. Maka dari itu, pendapatan dari SDA harus diarahkan untuk investasi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar kualitas hidup masyarakat naik.
PBB dan UNEP menyarankan transisi ke model ekonomi rendah karbon dan efisien sumber daya, di mana investasi publik dan swasta diarahkan pada infrastruktur bersih dan pelestarian ekosistem. Ekonomi hijau seperti ini bertujuan menumbuhkan lapangan kerja baru melalui investasi yang mengurangi emisi dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
Di sisi lain, arus globalisasi memperkuat persaingan atas sumber daya alam. Transisi ke energi hijau dapat memicu “perlombaan” atas mineral kritis seperti, lithium, kobalt dan nikel yang diperlukan baterai dan panel surya.
Menghadapi dilema ini, beberapa langkah terukur dapat diambil. Contohnya seperti penerapan ekonomi sirkular di industri fashion dengan mendorong daur ulang serat, memperpanjang usia pakai produk dan mendesain ulang rantai pasok supaya limbah dikurangi.
Sebagai konsumen, masyarakat dapat mengedepankan konsumsi lebih sedikit dan menerapkan 3R/4R yaitu, Reuse, Reduce, Repair, dan Recycle. Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu memperkuat aturan lingkungan dan infrastruktur daur ulang. Dengan demikian, kita membangun jalur tengah di mana ekonomi tetap tumbuh dan alam pun tetap terjaga.
Referensi:
- UN Environment Program, UN Alliance For Sustainable Fashion Addresses Damage Of “Fast Fashion”.
- Abul Muamar, Parade untuk Mendorong Fesyen Berkelanjutan dengan Kain Berpewarna Alami, 11 Oktober 2023, Green Network.
- Rashmila Maiti, The Environmental Impact of Fast Fashion, Explained, 20 Januari 2025, Earth.Org.
- Komunikasi LCDI, Mengenal Fesyen Sirkular Siklus Yang Mengubah Dinamika Dunia Mode, Low Carbon Development Indonesia, 8 Maret 2022.
- Mongabay, Laporan Terbaru: Sungai Citarum Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, 29 November 2012.
- Handoko, Central Java Villages Take Fast Fashion To The Cleaners At Indonesia’s Supreme Court, 26 Mei 2025.
- Fiori Rizki & Intan Anggita, Threading a Path Towards Sustainable Fashion in ASEAN, 19 Desember 2023.
- European Commission, EU Strategy For Sustainable and Circular Textiles.
- Nabila Assysyfa Nur, Menuju Circular Fashion: Perlunya Regulasi dan Penguatan Kerjasama, CWTSPSPD, 15 Juni 2025.
- ASEAN, 18th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 20th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
- Aswin Rivai, Degrowth Ekonomi dan Perubahan Iklim, Republik, 24 September 2021,
Redaksi menerima artikel opini dengan panjang cerita minimal 700 kata, dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail redaksibenua@gmail.com disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat.
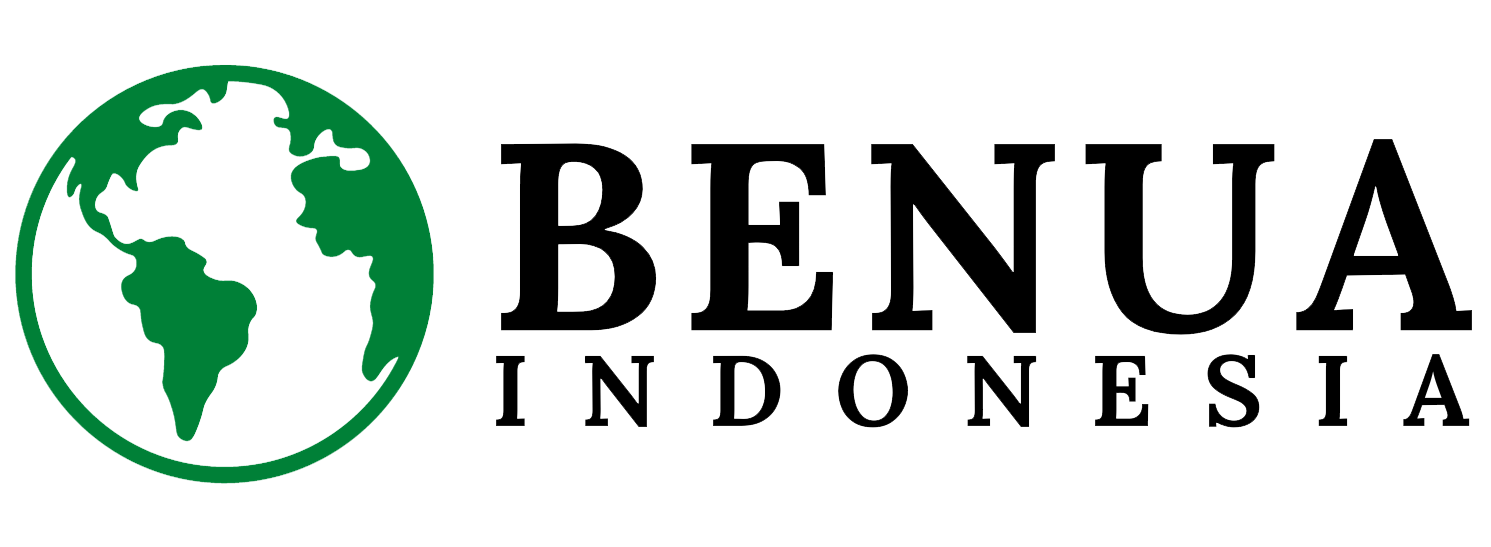













Leave a Reply
View Comments